Seporsi Gizi (?)

Sore itu, anakku pulang sekolah dengan senyum lebar dan perut kenyang. Katanya, ada “program makan gratis” dari pemerintah. Nasinya putih, lauknya telur rebus, ada sayur dan barang pasti juga tentu ada si “dia” katanya — diucapkannya dengan riang, seolah tak tahu bahwa kata “gratis” itu punya harga yang dibayar entah oleh siapa, entah dengan apa.
Aku hanya mengangguk, memaksakan senyum yang kaku. Di dompetku tinggal uang dua puluh ribu — itu pun harus cukup sampai akhir pekan. Tapi negara telah lebih dulu memberi makan anakku, bahkan sebelum aku sempat berpikir bagaimana caranya memberi makan keluargaku hari ini.
Aku, yang selama ini mencoba sekuat mungkin menjadi tiang rumah, kini tergeser oleh piring putih bersimbol garuda. Negara yang datang bukan dalam bentuk keadilan, bukan dalam bentuk lapangan kerja, bukan dalam bentuk harga pangan yang masuk akal — tapi dalam bentuk nasi dan telur rebus yang dikemas rapi dan disambut kamera.
Dulu, aku selalu bangga saat anakku berkata, “Ayah masaknya enak.” Sekarang, dia lebih banyak bercerita tentang makan siang di sekolah. Tentang menu bergizi, tentang relawan yang membagikan kotak makan, tentang foto bersama pejabat yang berdiri di depan spanduk bertuliskan janji. Bukan tentang ibunya yang menanak nasi, atau aku yang mengiris bawang di pagi hari.
Mungkin inilah zaman baru. Zaman ketika seorang ayah tak lagi dibutuhkan untuk menyuapi anaknya. Negara sudah mengambil alih — dengan lencana, kamera, dan niat mulia yang dipoles siarannya. Tapi tak ada satu pun dari mereka yang bertanya kenapa kami lapar.⸻Aku bekerja, tentu saja. Tapi upah itu tak lagi cukup menyalakan dapur setiap hari. Harga naik lebih cepat dari semangatku tiap pagi. Bahkan telur — yang dulu jadi makanan darurat — kini hanya hadir seminggu sekali. Sementara di layar kaca, mereka berkata rakyat harus bersyukur. Dan kami memang bersyukur, tapi dengan kepala menunduk, karena malu dilihat anak sendiri. Anakku tak tahu itu. Dia terlalu muda untuk tahu bagaimana harga diri bisa remuk bukan karena hinaan, tapi karena dibantu dengan cara yang terasa seperti ditertawakan.
Ada malam-malam ketika aku menatap piring kosong di rumah, sementara membayangkan anakku duduk rapi di sekolah, membuka kotak makan bantuan negara. Lalu aku bertanya dalam hati, dengan suara yang tak pernah bisa keluar lewat mulut: “Masih perlukah aku sebagai ayah, jika perut anakku pun kini bukan lagi tanggung jawabku?”⸻Istriku pernah berkata, mungkin ini jalan keluar. “Yang penting anak kita makan,” katanya. Dan aku tak bisa membantahnya. Tapi di balik kata-kata itu, aku merasa kehilangan sesuatu yang lebih besar dari sekadar peran: aku kehilangan kendali atas martabatku sendiri. Karena rupanya, ketika negara datang dengan nasi dan telur, ia juga perlahan menghapus fungsi manusia seperti ku — yang tak punya kekuasaan, tak punya suara, tak punya pilihan. Kami, orang-orang biasa, yang dulu percaya bahwa kerja keras cukup untuk bertahan hidup, kini jadi objek statistik: dicatat, diukur gizinya, difoto sedang makan, lalu dilupakan setelah pemilu lewat.⸻Hari itu aku ikut mengantar anakku ke sekolah. Bukan karena ada acara. Bukan karena ada waktu luang. Tapi karena aku ingin melihat langsung: dari tangan siapa sebenarnya nasi itu datang.
Dan aku melihatnya — si “dia” yang tersenyum ke kamera, sambil menyuapi satu sendok nasi ke mulut seorang anak. Anak orang lain. Anak siapa pun, agar terlihat hebat. Aku pulang lebih letih dari biasanya. Bukan karena jarak. Tapi karena satu kesadaran baru: bahwa dalam sistem ini, aku hanya diperlukan sejauh aku bisa diam dan bersyukur.
Dan ketika tak bisa lagi menyuapi anakku sendiri, maka mereka akan datang — bukan untuk bertanya apa yang bisa diperbaiki, tapi untuk mengambil gambar saat aku disingkirkan dengan sopan.⸻Malamnya, anakku berkata, “Besok katanya ada ayam, Yah. Dari program itu juga.” Aku tersenyum. Tapi di dalam diriku, aku merasa hancur. Bukan karena ayam itu. Tapi karena aku tahu, jika semua ini terus berlangsung, kelak anakku tak lagi melihat aku sebagai seseorang yang bisa memberi. Ia akan melihatku sebagai seseorang yang hanya berdiri, menyaksikan, dan bergantung pada belas kasihan yang diberi dengan nama kebijakan.
Dan itu jauh lebih pahit dari rasa lapar.
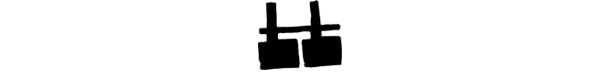
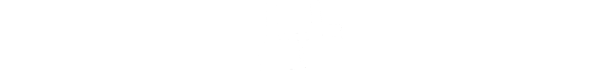

Comments ()