Sekumpulan Perdu di Bawah Rumah Terbang
Malam itu, bapak pulang ke pelukan ibu. Merepet ke relung hatinya dengan cara menyobek dada, lalu tenggelam dalam darah, menggenangi wajah yang telah bercampur ingus serta asin air mata.
Tangisannya terdengar seperti raungan. Wajah bapak tidak kelihatan dari bawah sini, tapi kami mendengar dengan telinga kami yang adalah dedaunan. Suara detak jantung ibu juga terdengar. Tubuh ibu menghangat oleh derap nadi yang mengencang, lalu melambat, kemudian lagi berderap. Mungkin ini suratan, jiwanya sebentar lagi tak lagi tertambat pada raga yang sudah penuh luka. Kebas. Atau bebas?
Tidak apa. Katanya.
Toh nanti subuh, ia akan terbangun, dengan telaten menjahit luka dadanya, bermodal benang jerami yang selalu disiapkan pada kaleng bekas monde butter cookies sejak empat lebaran lalu. Sembari menjahit, ibu akan terus bertanya: mengapa tetap memilih bersauh? Sedangkan rumah terbang ini sudah reyot, penuh lumut dan rayap, serta paku-paku di segala sudut engsel yang menyembul.
Tidak tahu. Begitu saja kami selewat menanggapi—lewat sayup angin yang menggoyang daun-daun—sebab kami adalah perdu.
Kata orang, ibu bermata teduh. Tapi kami tak tahu. Kami berada di bawah, tumbuh sebagai perdu. Dalam mata ibu, bersembunyi rimbun pohon mangga, ranum. Di balik rindang pepohonan itu, semut-semut merah berkoloni. Mereka suka mencubit kelenjar dalam mata ibu, membuatnya senewen meneteskan air mata tanpa disengaja. Kelopak matanya pun jadi sering bengkak. Dasar semut-semut nakal.
Tapi karena mangga ibu ranum, kami tidak jadi menaruh kasihan padanya. Biarkan mata dan batin ibu merimbun jadi kebun. Pada akar-akar pohon ibu, seorang laki-laki teronggok dan bersungkur, kedapatan tidur sambil mengorok. Membawa golok.
Laki-laki yang kami panggil bapak itu sering kali datang hanya untuk mencuri mangga (begitu kata ibu, disampaikan melalui bahasa daun dan angin pada kami, sang perdu). Laki-laki itu biasanya membawa karung, lalu mengutil segala wujud mangga: yang ranum maupun mengkal. Tak jarang, ia juga menebas ranting pohon dengan golok di tangannya. Sudah begitu, sebagian mangga akan ia makan. Sisanya ia bawa pergi entah ke mana. Lalu, setelah sejenak berjalan-jalan ke antah berantah, laki-laki itu akan kembali tersungkur di bawah pohon mangga dan tidur siang.
Mereka berdua tinggal di rumah yang melayang di udara. Rumah itu dibangun tanpa tiang, sehingga nyaris setiap bagiannya miring dan meleyot tak beraturan. Sedang kami adalah gerombolan perdu, tertinggal di atas bumi tua.
Rumah mereka bertengger tepat di atas kepala kami. Sebagai sekumpulan perdu, yang bisa kami lakukan hanya menonton pertunjukan rumah terbang saban hari. Kadang, rumah itu bergolak. Rumah terbang itu juga tak jarang bergemuruh seperti taifun, lalu berdebam, jatuh mengenai ranting dan daun kami hingga patah. Debu-debu, serpih dinding, kaca, kayu dari pintu, jendela, kamar, peralatan dapur juga ikut terpelanting ke bawah, meracuni tanah yang sebetulnya adalah jiwa kami.
Sering kali, kami mau pergi saja dari sini. Tapi apa daya, kami adalah sekumpulan perdu. Akar yang menopang kaki kami sudah terlampau dalam, mencengkeram tanah yang telah bertahun-tahun disiram air mata, darah.
Sebagai perdu, kami hanya bisa merayakan kehidupan dengan menari kecil, itupun jika diajak oleh angin. Angin sangat baik. Sering ia membawa kisah perjalanan melalui dongeng benih-benih. Hujan pun kawan kami, ia sering mengajak pesta minum es limun, juga makan kue yang dikudap di atas piring dan gelas yang dibuat dari tanah basah. Jikalau musim semi datang, kami juga akan berbunga. Di saat itu, kami saling memuji satu sama lain, dan melupakan bahwa ada rumah yang terbang-jatuh-bergemuruh di atas kepala kami.
Itu sudah lebih dari cukup. Kami memang tak bisa turut memetik ranum mangga di kebun mata ibu. Kami juga tidak bisa mengintip ibu merawat sobek dadanya yang penuh jahitan dan bercak kering darah. Tapi tidaklah mengapa. Bersama angin, tanah, hujan, bunga, dan benih yang mengasihi, kami sudah merasa penuh
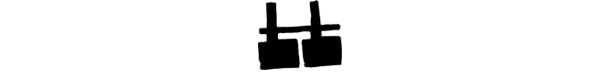
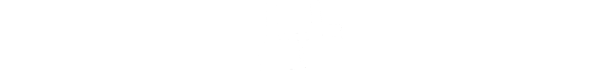

Comments ()