Sejoli Seblues
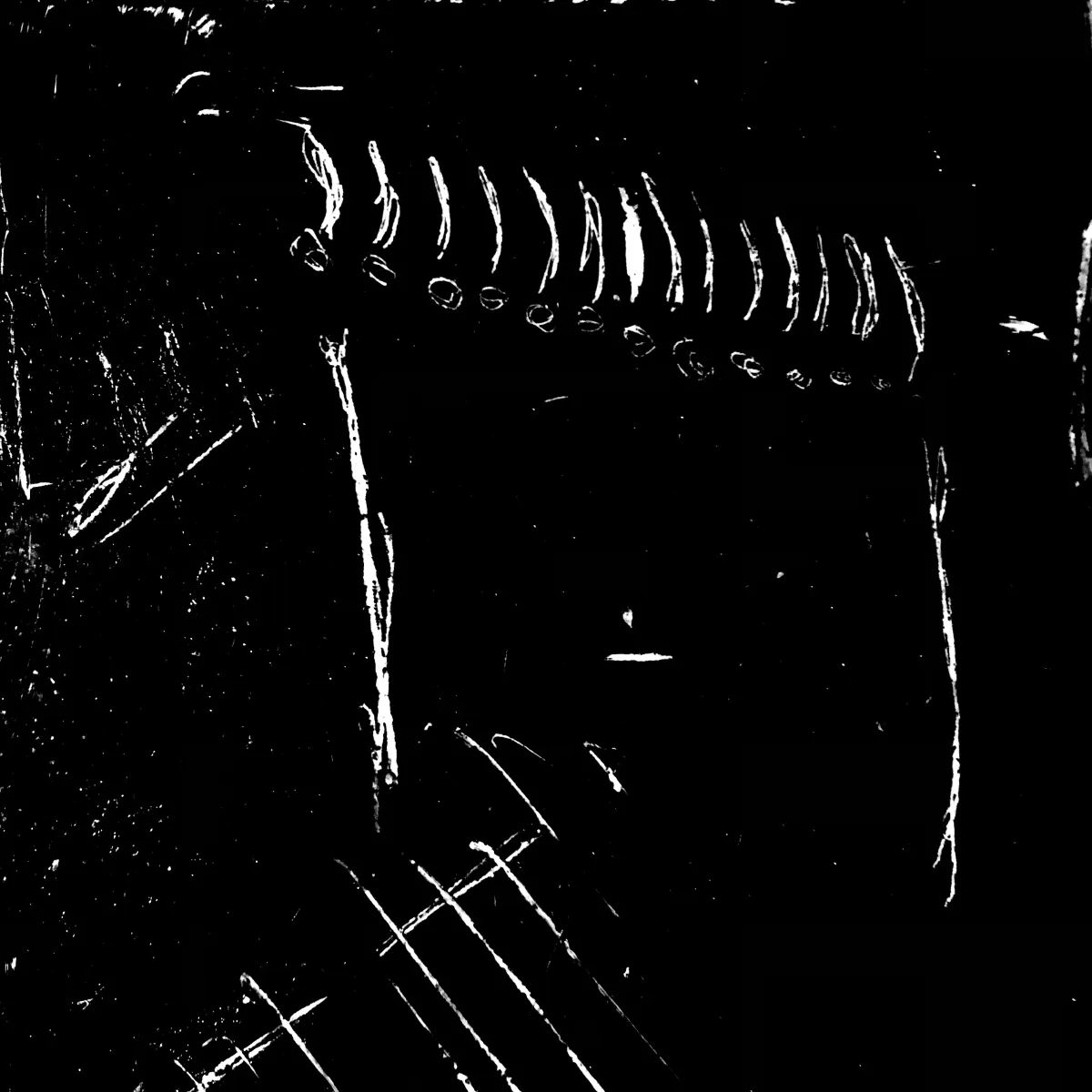
Saya tinggal di apartemen ini selama tujuh tahun lebih dua puluh sembilan hari. Sebelumnya tidak di sini, pindah-pindah. Ya, katakan saja ini tempat yang paling lama buat saya. Saya sebut ini gang – Gang Blues. Terpikirkan oleh saya ketika empatbulan pertama berada di sini. Apartemen saya berada di lantai tujuh nomor 132. Jendela saya menghadap langsung ke taman sempit dan jendela kamar apartemen seberang saya. Langit bisa jadi begitu cerah dan cepat tua. Tidak lama kemudian semakin mati dan hening. Gang ini begitu monoton namun paling mencolok. Jika senggang, saya selalu melakukan slow dance ditemani sigaret dan lagu Eddie Martin – Autumn Blues. Seperti saat ini.
When the leaves are turning gold
Bring back loneliness of old
Ini salah satu rutinitas saya ketika di kamar. Gerakan dan lagu yang sama. Saya sering bertanya pada diri saya sendiri: bagaimana mungkin setiap hari adalah baru ketika kita senang melakukan hal yang sama dari hari ke hari? Musik terus berlanjut dan dari ekor mata saya, penghuni lelaki di apartemen seberang juga senang memperhatikan saya menari dengan gerakan asal-asalan. Oh, tidak. Saya hanya mengikuti irama dan tempo musik. Kadang saya suka jadi pusat perhatiannya. Kadang tidak.
Pagi sekali saya harus berangkat kerja dengan baju dan kereta yang selalu sama juga. Melewati taman kecil Gang Blues setiap hari adalah menyaksikan mereka membagi diri kepada yang lain. Saya tidak tahu apa yang mereka bagi kepada sekawanannya, namun yang pasti, mereka hidup dalam ruang yang tidak tunggal. Mungkin juga saya dan lelaki itu. Tanpa sadar, kami saling berbagi atas apa yang tidak tampak wujudnya. Dalam perjalanan saya dengan berjalan kaki setiap hari, orang-orang menghitung waktu tanpa henti. Manusia mengalir seperti sungai, mendatangi dan meninggalkan gedung seperti kilat, kadang bagai merpati yang mampir ke air terjun kemudian siap menggelindingkan tubuhnya ke bawah dan semakin dalam hingga lebur. Kita selalu sama. Mengenakan warna baju sesuai urutan hari, mungkin juga suasana hati. Dengan kereta yang kecepatannya sewaktu- waktu berubah mengikuti obrolan manusia di dalamnya.
Saya menghitung dan mengamati orang-orang dari jarak yang sangat jauh sebelum mendekat. Ini saya lakukan ketika ingin bercengkrama atau mencari teman. Dalam keheningan. Beriringan dengan setiap jejak kaki dan waktu yang tidak pernah putus itu. Tidak jarang momen itu juga mengembalikan pikiran dan jiwa saya kepada Gang Blues. Kepada lelaki itu. Pertanyaan ‘apa kabar’ membuat saya harus terus menghitung di sekitar saya berada. Apa yang tampak. Apa yang tidak. Keduanya menjadi satu ruang tidak terpatah-patah. Kadang dalam perhitungan itu, rasanya saya jadi kabur. Kabur yang akhirnya membawa saya pada kenyataan: semua berada dalam satu komposisi. Mereka lebur, tapi menjadi baru ketika selesai dalam perhitungannya masing-masing. Suasana itu saya rasakan dalam sukma. Saya bawa pulang hingga tidur. Pada hari-hari kita yang dipaksa selesai, namun pada nyatanya belum, mungkin yang diperlukan hanya berjalan santai sambil menukil beberapa baris lirik lagu, sajak, atau sekadar membaca komposisi bahan makanan dan minuman yang dipunya. Mungkin membaca garis-garis setiap sudut ruangan. Mungkin sebaiknya tidak. Mungkin membaca ke mana arah mata kita dan seberapa dalam ia melihat. Mungkin juga tidak. Berkata ‘mungkin’ kadang tampak seperti kita adalah penakut. Kata itu menjawab bahwa ada ruang-ruang yang tidak diketahui dan tidak ingin dimasuki. Sisi lain, ia membawa kita pada suatu keadaan yang lepas.
Jika malam tiba, kita takut menampakkan wujud sejatinya diri kita. Melihat diri di cermin seperti monster membuat jendela kamar dipaksa tertutup rapat-rapat. Oh, lelaki itu. Bertahun-tahun saya dan dia di Gang Blues, belum pernah sekali pun kami bertegur sapa secara langsung. Lelaki itu datang dan tinggal di seberang apartemen saya ketika kurang lebih setahun setengah saya di sini. Beberapa hari kemudian dan sejak itu, kami saling berbicara dan mendengarkan dengan mata kami. Mungkin kami memiliki kesamaan. Mungkin tidak. Yang pasti ketika saya baru memutar Autumn Blues di malam hari, ia hadir. Ia bagai penonton dengan mata tajam dan khusyuk memperhatikan setiap gerakan slow dance saya. Awalnya saya heran dan sempat bertanya-tanya apakah lelaki itu tidak bosan menyaksikan rutinitas saya itu setiap malam. Namun akhirnya keheranan saya itu hilang dengan sendirinya. Melihat ia juga punya rutinitas melukis kadang bertepatan ketika saya menari. Biasanya setelah saya selesai. Objek-objek lukisannya luar biasa. Entah untuk menemani saya. Intinya, kami sama-sama tidak tergangia sering menampakkan dirinya dari seberang ketika ia sedang melukis ataupun setelah lukisannya selesai. Seperti saat ini, giliran saya mendengarkan lukisannya berbicara.
Sempurna. Dia andal dan lihai merekam setiap objek lukisannya. Objeknya selalu bergerak dan membuatnya hidup. Dari jendela ini, bisa dipastikan lelaki itu selalu kurang tidur. Entah berapa berapa banyak lukisan yang berhasil ia selesaikan selama bertahun-tahun kami saling menjangkau seperti ini. Tapi, apakah ia sadar bahwa ada yang kurang dari lukisan-lukisannya itu? Saya akui ia memiliki bakat yang luar biasa dalam melukis. Namun mungkin ini yang luput darinya. Entah ia sadar atau tidak, ia telah melakukan kesalahan fatal dalam karya-karyanya. Terlalu sempurna. Saya mengingat seorang kritikus bernama Giorgio Vasari yang menjuluki del Sarto dengan lukisan agungnya Madonna of the “Harpies Birth of the Virgin” sebagai ‘Pelukis Tanpa Keslahan’. del Sarto begitu detail dalam melukiskan objeknya hingga ia tidak menyadari bahwa ia diambang kehancuran. Sama halnya dengan lelaki seberang itu. Kelemahan dari lukisan-lukisannya adalah mereka selalu dan terlalu sempurna. Saya tidak pernah menemukan celah dari hasilnya ketika ia menampakkannya kepada saya. Ya, anggap saja saya orang awam yang tidak mengerti lukisan dan untuk menutupinya cukup dengan mengikuti pernyataan Giorgio Vasari.
Dari jendela ini juga, setiap kali ia selesai melukis tidak pernah saya melihat ia memajang lukisannya. Atau mungkin ia memajangnya di sisi yang tidak terlihat. Sepenglihatan saya dari sisi yang dapat dijangkau, ia hanya meletakkannya begitu saja di tempat yang sama ia melukisnya atau menyusunnya di sudut dinding. Kembali saya nyalakan sigaret. Menggepulkan asapnya ke langit.
Kami menutup satu ‘pintu’ yang sama. Bertahun-tahun. Sejak kami masing-masing di sini. Daun-daun setiap hari berguguran dan jatuhnya menjadi kuning, sementara kami kian hari terjebak dalam situasi ini, dalam ruang ini. Saya tidak tahu pintu manakah itu dari dirinya. Tiba-tiba ingin sekali saya merobek penanggalan di berlembar-lembar kertas di dinding kamar ini. Angka-angka itu membuat kita jadi terpaku akan besok yang tidak tahu panjang atau pendekkah ia mengikuti keberadaan kita. Kita dikejar oleh apa saja yang membuat kita takut. Satu-satunya cara adalah menutup pintu dan sendiri yang paling dalam. Begitu pun saya dan lelaki itu. Kami saling berkunjung sebatas jendela kamar, mata seperlunya karena takut-takut kami saling membaca terlalu dalam. Tapi tetap saja seperti ada zat lain yang membuat kami ‘saling’.
Waktu terus berlalu. Tengah malam di sini semakin pekat. Taman kecil terus menampakkan penghuninya. Mawar dan anggrek di situ bergerak mengikuti arus angin malam. Menari dan menghidupkan bagian-bagian dirinya yang tidak tampak ketika pagi atau sore hari. Dari sini, lampu-lampu jalan dan rumah hidup dan mati dengan irama. Yang saya lakukan hanya terus duduk diam dan meresapi apa yang terjadi sekarang ini, sejauh mata saya melihat dan mendengarkan. Menyadari bahwa saya dan lelaki itu telah terasing. Kami terasing dari hiruk-pikuk bahkan dalam keheningan. Dalam lubuk, kami terus melihat waktu dengan cara kami sendiri. Waktu kini dan kemarin yang entah apa jadinya di besok hari. Saya kemudian teringat lagu Bob Dylan yang berjudul I Countain Multitudes. Baris- barisnya mengingatkan saya akan akan pikiran-pikiran ini. Juga apartemen ini, meskipun sekarang saya tengah di sini. Menjelajahinya dari balkon kamar dengan mata terpejam.
I paint landscapes, I paint nudes
I countain multitudes
Kemungkinan-kemungkinan itu kembali hadir. Saya biarkan ia bergerak sendiri mengikuti arus angin. Bergerak tanpa tergesa-gesa. Saya tidak bisa memisahkan waktu kini dan waktu yang sudah lampau. Mereka membentuk ruang yang akhirnya kini saya tempati. Menjadi komposisi yang tidak terhingga dan tidak dapat dipatok.
Saya tidak tahu harus dibawa ke mana kemungkinan-kemungkinan itu. Yang saya lakukan hanya terus duduk di sini. Lelaki itu juga. Tidak tahu sekarang pukul berapa, yang pasti pekat tengah malam semakin menjadi-jadi.
Kami berada dalam keheningan tingkat khusyuk tertinggi. Dalam batasan jendela dan taman kecil, mata kami bertemu. Tiada lagi perhitungan apa-apa mulai detik ini dan nanti. Semua pergulatan telah selesai. Yang ada hanya asing membawa kami jauh ke dalam segala arah. Di Gang Blues ini, kami selesai. Lampu kami mati dan semakin gelap.
(Sedang dimainkan Gary B.B Coleman – The Sky is Crying di seluruh penjuru Gang Blues.)
Can you see the tears roll down the street
The sky is crying
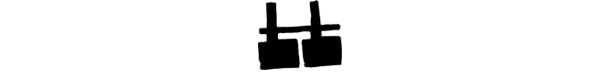
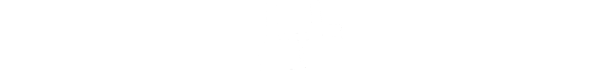

Comments ()