Ibu Penjaga Anak-Air-Gula
Suatu masa, lahirlah anak-air-gula. Ia doyan merengek jika tidak diminumi air hangat dicampur gula pasir yang belakangan harganya jadi tujuh kali lipat dibanding masa sebelumnya. Padahal, keluarga anak-air-gula tinggal di kota yang dipenuhi pabrik gula sejak zaman Belanda, menyisakan segala jenis masakan bertabur gula. Gula jadi sangat mahal, katanya karena resesi. Ah, masa iya? Kota ini dipenuhi tetangga yang suka menyuguh secangkir teh dengan dua sendok makan gula. Sungguh legit dan pekat. Jika ada tamu bertandang di akhir pekan atau lebaran, gula tiba-tiba menjadi lambang penghormatan tatkala tak bisa menyajikan Khong Guan yang terlampau mahal; atau terlanjur usang diisi rengginang. Juga seduhan kopi kapal api dicampur gula tiga sendok, dikocok dalam cangkir gagah yang ketika diseruput rasanya terlalu manis dan bikin mabuk kepayang. Sup, bobor kelor, oseng, opor, bahkan sayur singkong—ditaburi sekelumit gula pasir, konon agar rasanya lebih seimbang. Faktanya, tambahan gula justru membuat panganan itu jadi ambigu: asin tapi manis, manis tapi asin.
Resesi ataupun tidak, si anak-air-gula tak peduli. Ia sekarang malah sedang menangis, meraung, terus-terusan melepeh puting ibu. Dalam tangis patah-patah, ada makna tersembunyi, katanya, “aku..,oek, mau.. oek, air, oek, gula”. Ibu terus terang kebingungan karena kali ini hanya puting dan kelenjar susu saja yang ia miliki. Uangnya habis, sebab keburu bayar hutang kontrakan yang sudah nunggak tiga bulan sejak huru-hara demo di jalan raya ujung gang terjadi saban siang. Belakangan, ibu cuma sanggup beli beras, uyah, dan kecap manis saja. Kadang jika ada sedikit tambahan uang receh, ibu akan membeli kerupuk di warung kelontong sebelah. Kalau terpaksa, sesekali ia berhutang pada ibu pemilik warung. Kerupuk biasanya dibagi dua untuk dimakan bersama bapak yang kini hidup menganggur. Jika beruntung, satu bulan sekali, bapak diundang kumpul-kumpul oleh pak RT, dan biasanya mendapat gorengan gratis untuk makan malam ibu dan anak air gula.
Barangkali karena asupan snack micin membuat air susu ibu suka macet, atau jika keluar pun, rasanya hambar sungguh bagi si anak-air-gula. Entahlah. Ibu masih berusaha menempel-nempelkan putingnya pada mulut anak air gula, “ayo nak, ini sehat untukmu”, ujar ibu sembari menimbang gamang dalam suaranya. Sang anak tidak mau, karena ia adalah anak-air-gula. Menyerah, ibu menutup payudara dengan kutang yang kadung basah kena keringat, memilih mengalah kepada air hangat dan gula yang lebih mahal ketimbang badannya. Ia pergi ke warung kelontong sebentar, mengutang seperempat gula pasir. Sekembalinya ke kontrakan, ibu letakkan anak air gula di atas lantai, bergegas pergi ke dapur dengan legawa.
“Tak apalah kali ini aku kalah dengan air gula. Anakku mau minum pun sudah buatku lega”.
Kerompang, kerompang.
Suara dot beradu dengan panci mie instan dan gelas di rak piring sempit dapur yang menyatu dengan ruang tengah. Sang anak air gula tak sabar menyucup minuman kesukaannya, sehingga ia menguik sedikit. Ibu bergegas. Digodognya air dari keran sampai bergolak, lalu ia memasukkan air panas ke dalam dot, dicampur dengan air biasa dalam teko plastik. Ibu mencubit gula pasir. Satu sendok, dua sendok. Botol ditutup, lalu dikocok, dan siap disajikan.
“Ini nak, air gula kesukaanmu, barangkali memang jauh lebih enak ketimbang susu yang kau sedot dari putingku”.
Anak air gula menguik senang, “eh, eh”, mungkin artinya adalah, ‘betul, bu, aku sedang tidak ingin minum susu dari tubuhmu, rasanya seperti sari kerupuk’.
Dalam hati, ia menggumam lembut, ‘tidak apalah, selagi anakku tak mau, semoga bapakmu mau membantu menghabiskan jatah susu ketimbang mampat dan payudaraku nyeri..’
-o-
Hari ini anak air gula sedang dititipkan kepada nenek yang adalah pensiunan guru. Nenek tinggal di rumah lapuk berwarna hijau, kelak akan berlumur guratan pensil hitam tatkala sang anak sudah tumbuh agak besar dan jadi sedikit nakal.
“Hari ini ibu akan sibuk sebentar”, kata ibu kepada nenek.
Kesibukan ibu hari ini adalah pergi ke toko loak dalam rangka membeli baju-baju bekas yang akan dijual kembali di pasar minggu. Tujuannya tak lain menambah pendapatan bapak yang belakangan jadi pengangguran karena sibuk berdemo. Ibu pergi membawa plastik besar, dan menyeleksi baju mana yang layak dijual agak mahal.
Ini, itu, ini, itu. Kata ibu seraya menunjuk baju bekas pilihannya pada si penjual. Sret, sret, sret, tangan ibu dengan cekatan menggeser pakaian jelek, dan menyampirkan baju yang masih tampak bagus di lengan kiri, sebelum akhirnya ia masukkan ke dalam plastik.
“Kemarin ada demo lagi, lho, di Gejayan”, kata penjual berbasa-basi, melepas hening yang tadinya cuma beriring suara klik-klik jam dinding, brum-brum motor oprekan melewat, dan srat-sret suara kain. “Iya, saya jadi harus cari jalan memutar, takut ketabrak orang yang suka melenggang bawa-bawa spanduk” kata ibu, “suamimu apa kabar, masih demo juga?” pertanyaan si penjual menunjukkan betapa ibu sering kesana dan sudah cerita soal bapak.
Ibu menghela napas, “Iya. Kadang khawatir, tapi katanya demi masa depan bangsa. Cuma kalau dipikir-pikir, sebelum jauh-jauh buat negara, aku berharap dia juga berjuang mati-matian buat keluarga. Capek, lho, hidup hari-hari jual baju bekas. Tapi ya sudahlah, demi kerupuk, beras, gula, dan cita-cita beli susu formula yang nggak kesampaian..”
Kata-kata ibu terhenti karena ada pembeli lain menanyakan harga baju loak kepada penjual. Ibu bergegas membayar, lalu pulang demi mencuci baju-baju itu untuk dijual di pasar minggu nanti. Sampai di rumah, ia mendapati bapak sudah duduk di dalam rumah, merokok. Wajahnya kelihatan agak lelah. Ia berkeringat dan kulitnya agak gosong, “Halo, bapak”, “Halo, ibu”. Mereka saling menyapa lalu bapak melayangkan cium di dahi.
Bapak bau keringat dan matahari, ibu wangi sabun bercampur bau jamur pakaian bekas. Bapak menuntun ibu ke dalam kamar, dan mereka mulai bercinta dalam hening—sebab tembok triplek kontrakan murah mereka pastilah tak mampu menghadang erang dan desah. Mereka takut kedengaran oleh tetangga dan jadi malu karenanya.
-o-
Sebelum anak-air-gula lahir, bapak masih mengenyam pendidikan di fakultas eksak di suatu kampus tengah kota yang dirindangi pepohonan. Di kampus itu, mahasiswa kerap berkumpul. Kadang berdiskusi, tapi lebih sering berbisik. Kadang ada penjual bakso melewat, tetapi kata orang-orang, rasanya terlampau tawar. Tidak enak.
Ibu kuliah di fakultas yang sama dengan bapak. Namun, laiknya mahasiswa eksak, ibu lebih suka bergumul dalam ruang dinding putih sembari membaca buku tentang tanaman, lalu pulang ke rumah tepat ketika jam perkuliahan berakhir. Sedangkan bapak, hobinya melipir ke Sasana—tempat paling terkenal bagi gerombolan mahasiswa yang suka bergelora meneriakkan “Lawan”.
Bapak seringkali dilabeli sebagai pembelot. Kawan-kawannya lebih sering menyebutnya aktivis. Di kala mahasiswa dari fakultas sastra, ekonomi, filsafat, atau politik gembar-gembor demo dan berkumpul seperti gerombolan tikus dalam jaringan terowongan bawah tanah, bapak tampak seperti kucing kesasar dari sebuah rumah eksak putih bersih. Berbeda dengan ibu, yang adalah perempuan pendiam, hanya suka membaca buku tentang tanaman, dan dengan rok sepan berbalut kardigan berjalan mondar-mandir mencari angka-angka di atas kertas. Tubuh ibu senantiasa wangi karena nenek mewajibkan ia menyemprot parfum saban pagi. Katanya, sebagai mahasiswa, ibu harus dandan rapi, agar bisa mewakili citra keluarga nenek yang konon dulu adalah priayi.
Entah bagaimana dua kutub itu—bapak dan ibu—bisa bertemu. Yang jelas bukan lewat doa karena bapak jarang sembahyang. Mungkinkah ibu naksir bapak duluan? Atau bapak yang menyukai ibu karena gayanya memancarkan aura tatkala melenggang dengan rok sepan, mondar-mandir melalui kelas, laboratorium, dan gang kampus sambil membawa buku tentang tanaman.
Tidak tahu, dan agaknya tidak penting juga untuk tahu.
Tepat pada semester akhir kuliah, ketika mereka telah berpacaran, ibu mendengar keluarga bapak tepar. Bisnis kakak iparnya agak macet akibat resesi mulai menggerogoti. Simbah—ibu bapak—dituduh mencuri uang. Saat itu tentu saja bapak panik, stres. Masalahnya, kuliah bapak sedang mangkrak karena keseringan pergi ke Sasana, sekarang ditambah lagi dengan risiko tidak dapat uang bulanan. Penyebabnya, uang saku dari simbah sebentar lagi di setop sebagai buntut dari kriminalisasi terhadap simbah oleh kakak ipar bapak. Ibu—saat itu masih menjadi pacar bapak—mencoba menenangkan, “biarkan”, katanya, “biar bagaimanapun, aku akan terus menemanimu”. Bapak lega. Mereka semakin erat sejak saat itu. Pasti mereka tidak—atau belum tahu, cinta tak melulu murni akan kasih. Sebab tanpa duit, lambat laun cinta akan membusuk jadi sepah. Saat itu, masa depan sedang menertawai mereka.
Namun, bapak tetap ingin meneruskan perjuangan di laga jalanan. Ibu berusaha menyelesaikan kuliah tepat waktu karena nenek menuntut agar gelar priayi di keluarga tetap bisa dipertahankan melalui gengsi menjadi seorang sarjana. Bapak belum menyelesaikan kuliah, tetapi ibu sudah mentas. Ibu masih mendukung karir bapak—jika demo bisa disebut kerja—sebagai demonstran dari Sasana. Agaknya ibu tahu itu penting buat bapak, apalagi sekarang sering sekali ia ikut sedih melihat banyak orang diberitakan hilang, harga bahan juga jadi naik terus.
Keluarga bapak masih sulit. Pasca jadi buronan oleh anak mantunya sendiri, terpaksa simbah harus menjual rumah yang telah ia tinggali seumur hidup demi membayar ‘ganti rugi’ atas tindak kejahatan ilusif yang dilakukannya. Bapak baru tahu ternyata orang bisa biadab seperti itu. Ah, tentu biadab sudah jadi barang yang biasa-biasa saja, mengingat akhir-akhir ini terlampau banyak kekejian terjadi. Di rumah, kampus. Di jalanan. Jika cuma masalah tuduh-menuduh, pastilah itu hanya hal biasa.
Entah karena masih ingin berjuang, atau sekadar kepingin mengalihkan pikiran, bapak terus pergi ke Sasana dan ikut berteriak di jalan. Ibu tentu tetap percaya kepadanya. Hingga pada suatu hari, simbah menelepon bapak, bilang bahwa dia kudu cepat lulus, agar bisa kerja karena keluarga sudah tak sanggup mengirim uang saku. Katanya, simbah mulai kewalahan karena bapak sudah lima setengah tahun mendekam dalam kampus. Pikir simbah, bapak sudah saatnya mentas, seperti kakak-kakanya yang kini kerja di bank.
Di waktu nyaris bersamaan, dekanat mengundang bapak masuk ke ruangan serba putih. Bapak deg-degan. Ibu deg-degan. Angin berdesir pun jadi agak tersendat, ikut deg-degan. Keluar dari ruangan, bapak lesu. Tangan kirinya meremas surat ber cap kampus rakyat, isinya basa-basi ‘dengan hormat’, tetapi isi surat itu intinya hanya ada pada lima belas karakter huruf: anda dikeluarkan. Bapak dikeluarkan dari kampus yang selama ini menjadi rumah bagi harapan dan hidupnya.
Bukan, tentu ia tidak dikeluarkan karena karut-marut kondisi keuangan keluarga semata. Melainkan, bapak dikeluarkan dengan dalih menjaga ketertiban kampus. Menurut para pengajar di fakultas eksak (yang barangkali cuma cecunguk karena ketakutan diburu penggede), orang eksak harusnya bikin-bikin inovasi saja demi bangsa, bukan malah melawan negara. Bapak, sebagai sosok kurus dan hitam terbakar matahari itu harus menanggalkan mimpi memakai toga karena dianggap kisruh. Sekrup kecil bapak yang tadinya optimis menyangga kaki-kaki meja dunia, kini telah tanggal, menunggu giliran berkarat.
Hari itu ibu wisuda, tapi mukanya kelihatan agak lebam. Ia tutupi wajahnya dengan bedak kelly yang agak wangi, dan make up natural menyapu muka cantik ibu. Wajah itu memang jelita, tapi kok mata ibu menguarkan mimik gembira bercampur secarik ekspresi sedih? Ibu kenapa? Bapak datang belakangan, usai nenek dan kakek pulang. Mereka bertiga tak saling menyapa.
-o-
Sewaktu aku masih menjadi zat entah apa, ada seseorang (atau sesuatu?) yang suaranya bergema, menyelubungi diriku yang tak mengenal wujud, ‘halo’, katanya. Aku juga bilang halo, lewat pori-pori udara, sebab aku belum mengenal wujud, juga bentuk. Pengetahuan tentang wujud barangkali baru akan kuketahui belakangan, mungkin bertahun dari sekarang? Beratus tahun? Atau dalam rentang waktu yang tak selalu bisa kita perkirakan.
Suara itu bertanya, adakah aku siap mengalir menjadi energi baru? Aku menggeleng—dalam wujudku yang tak berwujud. Sambil tidak tahu, apa maksudnya mengalir menjadi energi baru. Namun suara itu—yang kini berwujud dalam zat—yang tak juga berwujud—tampak menyungging senyum, ia mulai menghilang. Ruangku tiba-tiba terasa hampa, aku ditinggalkan di tengah rongga waktu tak berujung. Kelihatannya, dia berhenti memaksaku mengalir menjadi energi baru.
Hingga pada suatu masa, zatku diajak piknik turun ke bumi, bersama dengan angin yang hari itu membawa bibit rumput dan bunga. Berada dalam kesatuan angin, aku merasai desir gembira air yang kala itu kusapa (hingga mereka beriak-riak girang, mungkin ingin kenalan karena aku belum pernah mampir ke bumi); rumput meneriakkan salam lewat benih terbang; juga bau kue-kue manis, dan comberan memeluk hangat. Aku cukup bahagia. Hingga akhirnya, sebagai angin, aku melewati suara aneh. Aku tidak tahu itu apa, karena kedengarannya lamat sekali. Tapi lama-lama, suara tersebut mendekat. Itu adalah tangis. Dan tangis itu, terasa sangat dekat dan familiar. Itu suara.. Ibu.
Kemudian ada suara lain. Plak, plak, plak. Suara tepuk, lalu teriakan, caci maki. Hanya sedikit kudengar kata-kata macam ‘dungu’, ‘bodoh’, keluar dari mulutnya. Suara laki-laki yang tidak kutahu siapa, tapi juga rasanya sudah kukenal selamanya. Siapa dia?
Ibu yang belum pernah kutahu wajahnya, sedang menangis. Aku tak punya mata karena tak berwujud. Aku menyatu dengan angin, tapi bisa mendengar ibu menangis. Aku tidak tahu apa yang ia tangiskan, tetapi aku ikut sedih. Sayangnya, aku tidak bisa berlama-lama berada di tempat ini. Meski aku sangat ingin tinggal dan menghiburnya. Kuucapkan selamat tinggal dengan menyeka wajah ibu lewat hembus lembut pada rona pipinya. Pulang ke dalam relung zat, aku bilang pada suara yang pernah mengajakku berbincang. Memanggilnya dalam suara, aku minta izin untuk diturunkan ke bumi. Aku ingin bertemu ibu, menemani dan menghiburnya, seperti janjiku sewaktu berhembus bersama angin.
-o-
Sewaktu aku lahir, bapak disebut sebagai aktivis—entah apa maknanya. Yang jelas, menjadi aktivis membuat ia dikeluarkan dari kampus yang telah membesarkan harapan, dan memupuk geloranya lewat laga Sasana. Ibu turut kena getah. Usai kuliah, ia mendaftar jadi calon pengajar, dihantarkan oleh buku kesayangannya tentang tanaman. Tiba-tiba, karena mengetahui bapak adalah pacar ibu, ia pun dicoret dari daftar nama kandidat. Ibu sedih, tetapi tidak menyerah, sebab di dalam perut ibu saat itu, ada zat yang kelak menjadi anak air gula. Ibu lantas coba peruntungan menulis artikel tentang tanaman dan obat mujarab di koran. Ia senang, karena tulisannya diterbitkan, dibaca banyak orang, meskipun ia hanya mendapat honor kecil sekali.
Namun tiba-tiba, ia harus berhenti karena penerbit koran gulung tukar. Mereka bilang tidak lagi sanggup membayar karyawan, apalagi tulisan. Sejak itu koran-koran tak lagi dicetak, dan tulisan ibu tidak pernah lagi terbit. Ia tidak punya cukup uang untuk beli sayur, beras, minyak goreng, telur, daging, apalagi susu. Ia cuma bisa beli segenggam beras dan kerupuk, juga gula untuk bikin kopi atau teh. Di sela-sela kebingungan, ibu berjalan kaki (tentu bersamaku di gendongan), dan bertemu penjual pakaian loak. Dengan kepala yang terus dipenuhi pertanyaan akan: “besok makan apa?”, membuat ibu memutuskan untuk menjual pakaian bekas di pasar minggu demi menyambung napas. Pikir ibu, di masa paling krisis sekali pun, orang pasti butuh pakaian. Tak harus mahal, bahkan dari karung goni macam zaman penjajahan Jepang pun bakal dipakai. Apalagi, jika bukan goni, bagus, dan murah seperti ini. Ibu akhirnya menafkahi kami dengan menjual baju di pasar minggu, melalui jalur-jalur yang jarang dilalui para demonstran, sebab ia tidak suka keramaian dan tidak pandai berdemo. Berbeda dengan bapak yang berbau jalan dan matahari—kadang baunya apak bercampur sepercik aroma bekas gas air mata. Ah, kasihan bapak.
Tatkala sesiangan aku meraung dengan bibirku yang kecil dan cerewet, ibu pergi ke dapur dan mulai menggodog air, niatnya membuat teh untuk dirinya yang agak capek mengurus rumah dan dagangan di pasar minggu. Namun entah kenapa, tiba-tiba ia menuang juga air panas ke dalam botol dot milikku, mencampurkannya dengan air di teko, dan menambahkan gula. Ibu lalu menjejalkan air gula kepadaku yang tengah meraung, sembari ia minum teh di tengah udara permukiman Caturtunggal yang agak semilir sore itu. “Oek..oek” Aku mulai diam dan menguik pelan, sebenarnya mau bilang enak. Ibu menatapku, ternyata dia paham maksudku. Aku suka air gula. Sejak saat itu, aku menjadi anak air gula. Terima kasih gula. Tanpamu, mungkin raunganku akan terus menyobek hari hingga aku sendiri mati.
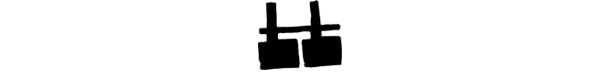
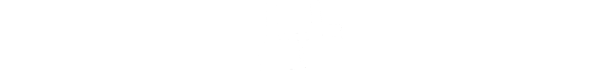


Comments ()