Di Apartemen Impianku
**
Apapun yang aku lakukan tidak pernah membuat orang lain puas. Apa mungkin karena aku membuat sebuah karya seni rupa? Apalagi yang aku buat ini betul buruk adanya. Katanya, entah kata siapa, seni rupa itu ditahbiskan sebagai sebuah ungkapan personal yang hakiki; ekspresi diri yang terpenjara oleh kefanaan manusia. Tapi aku pikir itu hanya gosip kacangan di lingkungan sosial seni rupa yang eksklusif. Lagi pula siapa yang bisa tahu kalau lingkungannya eksklusif? Jadi aku pikir hal itu masih semacam narasi Hitler yang katanya mati di Garut, atau harta Soekarno yang ada di Bank negara Swiss; aku tidak mengetahui betul hal itu kalau tidak ada orang-orang yang meyakininya bertemu denganku secara sembarang lalu membicarakan hal itu kemudian membuat diriku termenung menatap wajahnya yang susah payah membuat ekspresi yang dapat meyakinkan keyakinanku yang aku saja lupa letaknya di mana. Mungkinkah itu yang membuat apapun yang aku lakukan tidak akan membuat orang lain puas? Lupa letak dimana keyakinanku...
**
Aku terbangun. Ini hari yang cerah, rasaku. cangkir kopi pertama diisi saat aku menatap jam yang menunjukan pukul tujuh pagi. masih terlalu pagi untuk memikirkan...atau mungkin mengingat?
Sebuah ruang tiga lantai berbentuk segi enam dengan dinding berwarna hijau, setengah dari tinggi dinding tiap lantai dilapisi keramik berwarna hijau yang lebih gelap, lantainya berwarna merah gelap, namun dua lantai di atas lantai dasar dibobol. Jika dua lantai itu bolong, dalamnya ruang itu sekitar enam meter. Perabotan yang ada di bagian samping tiga ruangan itu masih tertata rapi, kecuali perabotan yang ada di bagian tengah lantai dua dan tiga; berantakan karena saling tindih di lantai dasar. Tiba-tiba ada seseorang yang datang begitu saja dan menghempaskan tubuhku sampai hampir jatuh ke dalam 3 ruangan tersebut. Orang itu berkata: ini adalah sebuah kolam ikan; sekarang. Dulu bangunan ini adalah sebuah rumah, dibuat oleh tangan seorang bapak. Rumah ini dibuat untuk memberikan keluarganya ruang, lantai dasar adalah ruang bagi ibu dan bapak, lantai dua adalah ruang untuk anak pertama dan lantai tiga adalah ruang untuk anak kedua. Kehidupan keluarga itu hanya terbatas dari tiga ruangan rumah tersebut. Untuk membeli kebutuhan hidup dan mencari nafkah, hanya sang bapak yang keluar dari rumah. Sang bapak berpesan kepada keluarganya: ruang–ruang yang ada di luar dari tiga ruangan rumah mereka tidak akan bisa memberikan belas kasih kepada keluarga.
Sambil membetulkan posisiku yang hampir jatuh dari atap lantai tiga, aku mendengarkan ceritanya. Dia melanjutkan ceritanya: Ketika anak kedua mencapai usia dua puluh tiga, ia mendapat sebuah mimpi. Sebuah impian di luar ruangan: Ada berbagai macam perabotan yang tidak itu–itu saja, ada orang–orang yang tidak itu–itu saja, ada kegiatan yang tidak itu–itu saja, ada kehidupan yang tidak itu–itu saja. Anak kedua menceritakan mimpinya pada sang bapak dan sang ibu, walaupun kakaknya sudah melarang anak kedua untuk menceritakan mimpinya kepada bapak dan ibu. Impian anak kedua yang telah diceritakan tersebut membuat sang bapak dan ibu menangis dan melebur ke dalam lantai dasar. Rumah itu bergoyang seperti terkena gempa berkekuatan tinggi. Air mulai keluar dari sela–sela lantai dasar. Anak pertama mencoba menyelamatkan anak kedua. Saat mereka sampai di lantai tiga dan mencoba membobol atap, air sudah hampir memenuhi tiga lantai rumah tersebut. Lubang yang dibobol hanya cukup untuk tubuh anak kedua. Kemudian anak pertama mengeluarkan adiknya tanpa sempat menyelamatkan dirinya sendiri.
Bagaimana dengan kolam ikan?
Setelah diselamatkan oleh kakaknya, anak kedua mencoba mencari pertolongan. Ini adalah sebuah peristiwa penting sekaligus menyedihkan: anak kedua dapat melihat impiannya, ruangan di luar tiga ruang di rumahnya. Namun ia harus kehilangan seluruh keluarganya. Saat itu juga ia baru menyadari bahwa rumahnya itu tidak seperti rumah lain yang ada di sekitar. Atap lantai tiga adalah permukaan tanah yang rumah lain pijak. Ia mencoba meminta pertolongan pada rumah–rumah yang ada di sekitar, dengan cukupnya pertolongan akhirnya atap lantai tiga bisa dibobol. Namun tubuh anak pertama tidak ditemukan. Anak kedua duduk termenung. Meratapi peristiwa penting sekaligus menyedihkan yang dialaminya. Saat ia menatap kosong permukaan air yang mengisi rumahnya, ia melihat sekelebatan bayangan yang bergerak cepat di dalam air. Ia mendekatkan wajahnya ke permukaan air, tetapi bayangan tersebut belum cukup jelas untuk dilihat oleh matanya. Ia pun membenamkan kepalanya ke dalam air. Kini bayangan itu sudah tak nampak lagi sebagai bayangan, itu adalah ribuan ekor ikan mas yang berenang memenuhi tiga ruangan rumahnya.
Lalu, kemana semua ikan mas dan air yang memenuhi tiga ruangan rumah ini?
Kini anak kedua menjalani impiannya; di luar tiga ruang rumahnya. Kini ia bisa melihat berbagai macam perabotan yang tidak itu–itu saja. Bertemu orang–orang yang tidak itu–itu saja. Melakukan kegiatan yang tidak itu–itu saja. Menjalani kehidupan yang tidak itu–itu saja. Ia cukup pintar untuk dapat mengetahui bagaimana cara hal–hal bekerja di ruang yang ia impikan. Ia menjual ikan–ikan mas untuk memenuhi kebutuhan sehari–hari dan kebutuhan impiannya. Satu tahun ia menjalani impian. Ia menemukan begitu banyak sensasi asing yang membuat sesuatu dalam dadanya bergetar. Ia menyukainya. Dua tahun ia menjalani impian. Ia menemukan lebih banyak sensasi asing yang membuat seluruh tubuhnya bergetar. Ia semakin menyukainya. Tiga, empat, lima, sepuluh, lima belas, dua puluh: ia menyadari tiap ekor ikan dan air yang semakin berkurang. Hingga akhirnya semuanya habis. Menyadari apa yang ia miliki telah habis. Ia duduk di mulut atap lantai tiga, memandangi lantai dasar, lantai dua, lantai tiga, dinding dan perabotan yang lembab, lumut yang berkerumun di sebagian pojok ruang. Kemudian ia merogoh kantong celananya: dua puluh ribu. Masih ada hari esok. Masih ada ruang yang belum ia lihat dan alami. Dua hari ia memandangi rumahnya yang kosong tanpa ikan dan air. Tanpa makan dan minum. Ia hanya memandang; kemudian berpikir. Kemudian terpikir. Kemudian jelas. Kemudian terjelaskan.
Kemudian apa yang jelas? Apa yang ia pikirkan? Apa yang terpikir olehnya? Bagaimana nasib anak kedua itu pada akhirnya?
Ia mengingat kembali berapa jumlah uang yang pernah ia dapat dari menjual ikan. Ia cukup pintar untuk dapat mengkalkulasikan secara sederhana berapa jumlah ikan yang pernah ada di rumahnya dari jumlah uang yang ia dapat. Jumlahnya tiga ribu ekor ikan. Air yang memenuhi rumahnya berkurang tiap senti mengikuti jumlah ikan yang berkurang. Bagaimana semua ikan dan air itu bisa ada di rumahnya? Itu yang ia sedang incar dalam pikirannya. Ia kembali mengingat kejadian saat keluarganya tiba–tiba melebur ke dalam rumah itu. Jumlah ikan yang ada sama dengan jumlah keluarganya yang telah melebur ke dalam rumah itu dikali seribu. Jadi ia menyimpulkan bahwa ikan dan air dapat mengisi kembali tiga lantai rumahnya jika ada orang yang melebur ke dalam rumah itu. Saat ini, belum ada orang yang melebur ke dalam rumah. Dan ia sedang mencari orang yang cukup sial untuk dapat ia dorong hingga jatuh ke lantai dasar.
Mendengar akhir kisah dari seorang yang bertubuh kurus dan tinggi itu aku menyadari posisiku yang sedang berada di mulut atap lantai tiga. Tanpa sempat untuk mempersiapkan tubuhku untuk merespons sebuah interaksi fisik yang mendadak, ia mendorong tubuhku ke dalam rumah dengan tiga ruangan itu. Aku terjatuh, melihat ke lantai dasar. Aku akan mati...bukan, melebur? Menjadi air? Menjadi ikan? Lalu dijual? Beberapa senti lagi aku akan menyentuh lantai dasar. Tidak ada kilasan gambar seumur hidupku yang terlintas saat aku menunggu kematianku? Melebur? Menjadi air? Menjadi ikan? Lalu dijual?
**
Aku terbangun. Ini hari yang cerah, rasaku. cangkir kopi kedua telah diisi saat aku menatap jam yang menunjukan pukul delapan pagi. masih terlalu pagi untuk memikirkan...atau mungkin mengingat?
Aku akan kedatangan tamu, penyair yang aku kagumi ternyata sudi untuk mengunjungi apartemen impianku. Aku menata bagian–bagian ruang yang berantakan. Aku menyiapkan satu teko kopi hitam, satu teko teh melati, empat lembar roti panggang dan tiga bungkus rokok keretek. Aku menyiapkan koleksi piringan hitam terbaik yang aku miliki. Balkon apartemen pun aku rapikan, aku letakan satu buah meja dan dua buah kursi. Yang terakhir, aku sudah memesan satu botol anggur terbaik yang bisa aku beli dengan uangku yang pas–pasan.
Aku sudah lama mengagumi penyair ini dengan malu–malu. Aku tidak pernah berani menegur atau mengungkapkan beberapa kata untuk menggambarkan betapa senangnya aku bisa bertemu berkali–kali dengannya. Aku hanya bisa memperhatikan kepalanya yang botak, pakaian dan sepatunya yang rapi dan trendy, caranya berdiri, caranya berbicara dengan orang lain, caranya menyedot rokok keretek dan menghembuskan asap dari mulutnya, caranya memegang gelas yang berisi anggur, caranya melamun di tengah perbincangan. Aku hanya memperhatikan untuk dapat membayangkan apa yang ada dalam pikirannya tanpa pernah tahu bagaimana cara aku dapat berinteraksi dengannya.
Interaksi pertamaku dengannya terwujud dalam sebuah malam pembukaan pameran tunggal Seorang perupa maestro yang digelar di sebuah galeri seni rupa yang terkenal. Suasana pembukaan sangat ramai dan mewah. Orang–orang saling berhadapan, berkerumun, mengobrol, memandangi lukisan, memandangi orang–orang, meminum anggur dan membicarakan nilai–nilai ideal estetika. Aku selalu merasa gelisah dalam keadaan ramai, jika ada acara pembukaan pameran yang ramai semacam ini, biasanya aku akan mencari bar minuman keras atau tempat–tempat yang terlupakan oleh kerumunan. Rasa gelisah seperti muncul begitu saja berbarengan dengan segala refleksi diri yang meludahi pikiran dan perasaanku. Aku memang bukan seorang perupa yang berprestasi, bisa hadir dalam acara pembukaan pameran ini saja karena beban moralku pernah belajar kepada sang maestro sewaktu dulu. Tapi yang aku beri pada sang maestro hanyalah sebuah kekecewaan yang selalu aku waspadai keluar dari mulut orang–orang dalam keramaian itu. Hanya minuman keras yang bisa meredakan kegelisahan dan ludah–ludah dalam pikiran dan perasaanku saat ini. Aku ingin minuman keras! Satu gelas anggur aku ambil. Hanya ada anggur, tidak ada vodka atau yang lain yang lebih keras dan dapat menyentak kepalaku. Dari belakang terdengar suara seorang wanita yang meminta tolong mengambilkan satu gelas anggur karena aku berada tepat di depannya. Aku membalikkan badanku ke belakang seraya memberikan satu gelas anggur padanya. Ternyata ia adalah mantan pacarku; berdampingan dengan sang penyair yang aku kagumi. Sebuah pertemuan sembarang yang agak mengganggu perasaanku tetapi lumayan menyenangkan. Mantan pacarku memperkenalkan pacar barunya: sang penyair. Terpaksa aku terlibat percakapan dengan mereka berdua. Aku melawak, berbohong, tersenyum, tertawa, kemudian membalikkan kembali badanku ke bar saat mereka berdua pergi untuk kembali menikmati lukisan yang dipamerkan. Aku meneguk bergelas–gelas anggur malam itu.
**
Aku terbangun. Ini hari yang cerah, rasaku. cangkir kopi ketiga telah diisi saat aku menatap jam yang menunjukan pukul sembilan pagi. masih terlalu pagi untuk memikirkan...atau mungkin mengingat?
Aku akan kedatangan tamu, penyair yang aku kagumi ternyata sudi untuk mengunjungi apartemen impianku. Bel pintu berbunyi, sang penyair telah tiba. Kubuka pintu dan mempersilahkannya masuk. Saat kutatap wajahnya, sebuah pertanyaan tiba–tiba meletup dalam otakku: bagaimana cara aku mengundang ia untuk datang ke apartemenku?
Wajahnya datar, tanpa menunjukan suatu emosi tertentu. Bukan berarti ia tidak ramah, ia sangat ramah dan sopan. Aku menawari kopi hitam, teh melati, roti panggang dan rokok keretek. Ia memilih kopi hitam dan satu bungkus rokok keretek, ia sudah sarapan sebelum pergi ke sini katanya. Kami duduk di ruang tengah, melakukan serangkaian ritual basa–basi dan percakapan basa–basi. Pertanyaan “bagaimana cara aku mengundang ia untuk datang ke apartemenku?” masih menggerayangi pikiranku saat aku bercakap basa–basi dengannya.
Ritual dan percakapan basa–basi memecah kecanggungan kami. Sang penyair pun memulai percakapan inti dalam kunjungan sosialnya. Ia hendak menjawab pertanyaan–pertanyaan yang ingin aku tanyakan padanya. “Pertanyaan apa?” pikirku “apakah pertanyaan tentang bagaimana ia bisa menjalin hubungan dengan mantan pacarku? Atau pertanyaan seputar puisinya yang aku sukai? Atau pertanyaan bagaimana cara aku mengundang ia untuk datang kemari?” Aku tersenyum, duduk di hadapannya dengan kaki menyilang kemudian menaruh siku di paha dan menaruh dagu di punggung pergelangan tangan. Musik yang mengalun dari pemutar piringan hitam sudah selesai.
Diam berdiri di hadapan kami berdua yang duduk berhadapan.
Kemudian diam pergi.
“Tentang bahasa? Tentang kata? Tentang puisi? Atau kesepian? Atau ludah?” Tanya sang penyair. Mungkin sang penyair datang untuk membahas proses kreatifnya denganku. Aku sudahi saja semua pertanyaan ragu dalam pikiranku. Aku pun menanyakan semua pertanyaan yang aku catat dalam buku catatanku ketika membaca karya–karyanya. Tiap kali sang penyair menjawab pertanyaanku, aku tidak bisa mendengar apa yang ia katakan. Suara sirine tiba–tiba muncul saat ia berbicara. Seperti tidak menyadari adanya suara sirine, sang penyair terus berbicara, menjawab pertanyaan–pertanyaanku; Semua pertanyaanku dijawab oleh sirine. Aku mencoba mencari satu huruf yang bisa aku pahami saat sirine mencoba menjawab pertanyaanku kepada sang penyair. Tidak ada satupun huruf yang bisa aku pahami dari sirine yang menjawab pertanyaanku kepada sang penyair. Sial. Bagaimana kalau aku memperhatikan bibir sang penyair untuk mencari satu kata yang bisa aku pahami? Lantas aku perhatikan bibir sang penyair yang sedang berbicara. Tetapi suara sirine tiba–tiba hilang, kini suara sang penyair bisa aku dengar. “Coba kau lihat ke balkon, apakah ada sebuah peristiwa di persimpangan depan? Aku mencari suara sirine.” Aku pun menuruti perintah sang penyair, aku pergi menuju balkon dan melihat ke persimpangan yang ada di samping gedung apartemenku. Persimpangan ini terlihat tidak asing, tetapi tidak terlihat seperti kenyataan. Persimpangan ini seperti pernah aku lihat, atau memang aku sering melihatnya karena gedung apartemenku berada di persimpangan ini? Tidak, persimpangan ini adalah sebuah foto yang digunakan sebagai cover album grup musik yang sedang aku dengar di pemutar piringan hitam. Suara sirine mendekat, kemudian ada dihadapanku, kemudian menjauh, kemudian...
**
Aku terbangun. Ini hari yang cerah, rasaku. cangkir kopi telah kosong saat aku menatap jam yang menunjukan pukul dua belas siang. Sudah terlalu siang untuk memikirkan...atau mungkin mengingat? Sial, aku harus mencari pekerjaan.
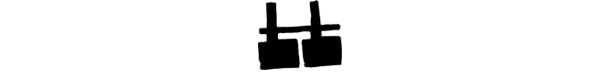
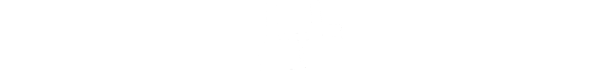
Comments ()