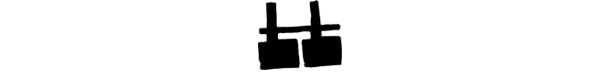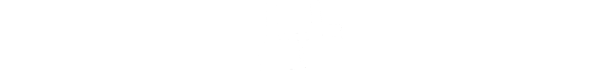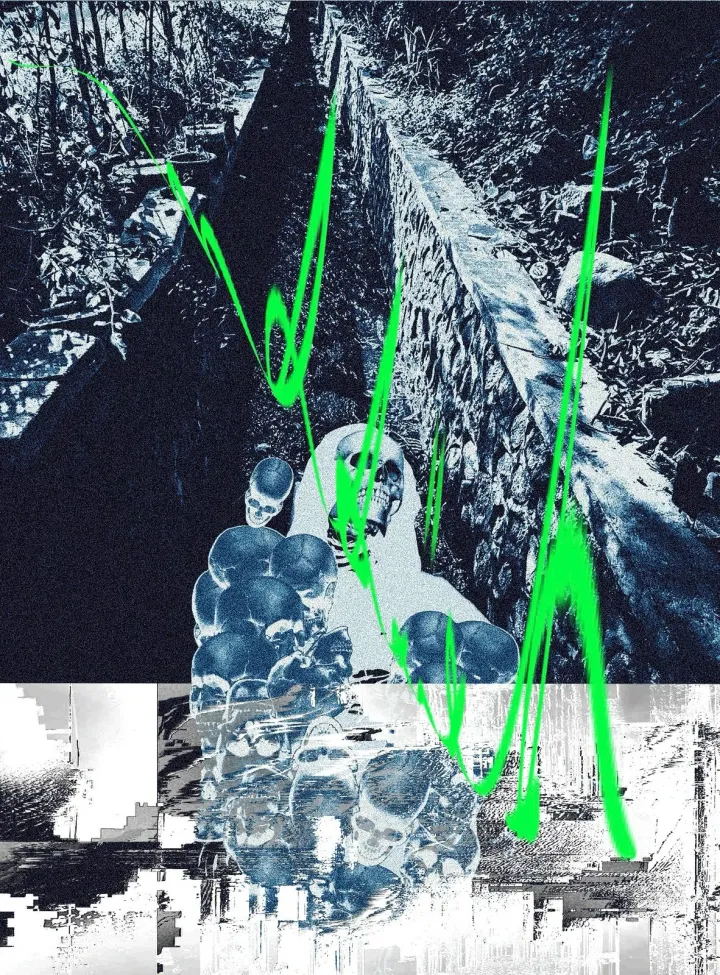Batu Kuda
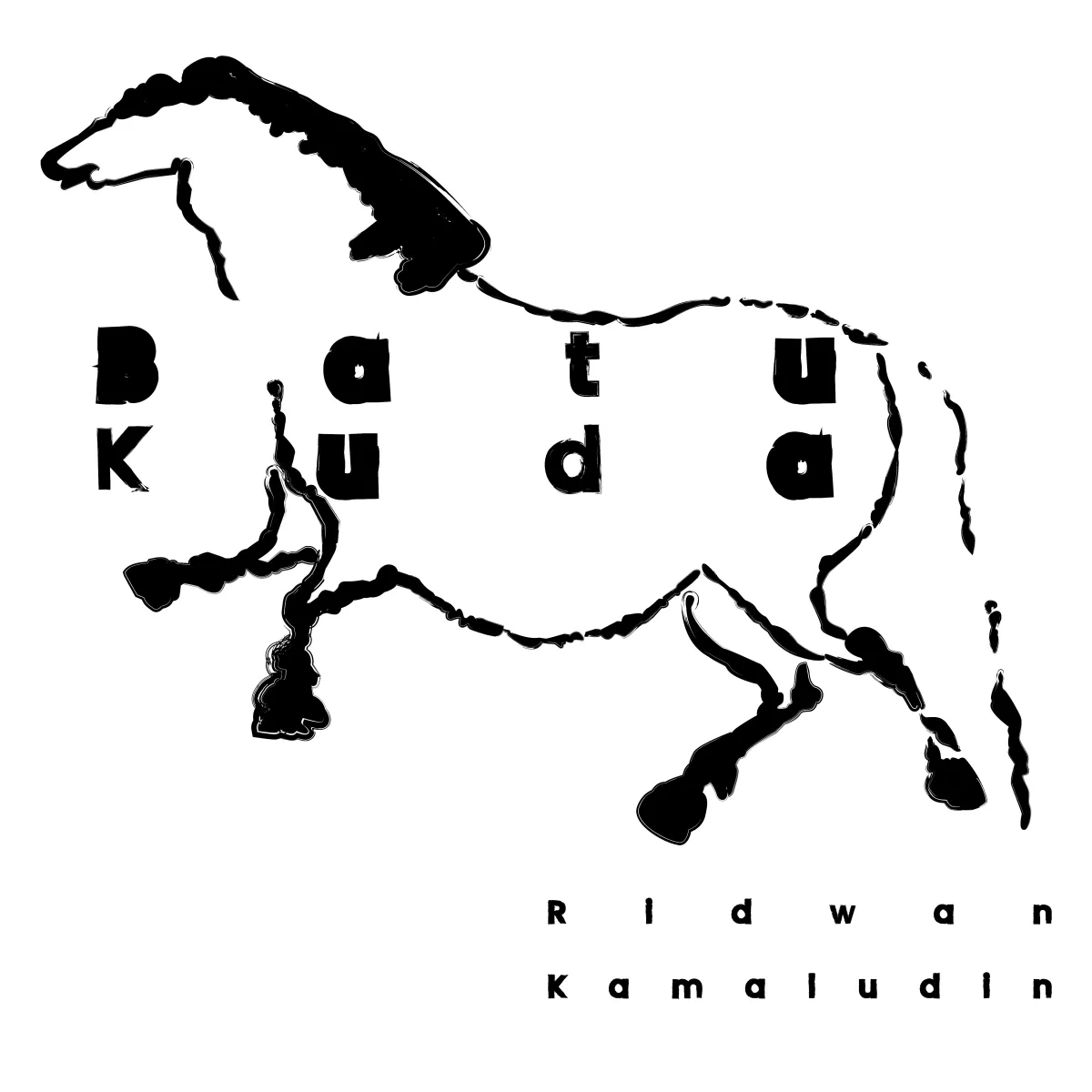
Saya tidak nafsu untuk makan belakangan waktu ini! Minat untuk mengunyah, memberikan asupan nutrisi pada tubuh, rasanya turun seketika, kalau tidak berlebihan, benar-benar anjlok. Yang buat makin risau, menjalar pula pada tidur, kadang kala membikin lamunan yang celaka. Saya tak ubahnya seperti kambing yang besok bakal disembelih, mata melongo, dada berdebar, waktu serupa golok tajam yang membayang.
Tetapi tedas, saya bukan hewan! Musababnya berbeda pula.
Dapat dipastikan, hanya terdapat satu muara alasan; karena gundah hati melihat nyata. Sebuah kondisi berkenaan dengan anak sendiri yang belakangan waktu, tepatnya tanggal dua puluh dua nanti, akan genap menginjak angka dua puluh enam hari.
Nomor yang menunjukan saya tidak pernah melihat kembali senyum dari bibirnya. “Kenapa ibu sama dengan manusia lainnya?! Selalu khawatir dengan wajah dingin!! Kemudian ditafsirkan dengan ke babak beluran!! Ibu, tengok, aku sungguh baik-baik saja. Mohon, Bu, jangan lebay!!”. Tanggapan demikian keluar dari mulutnya yang mungil, dibarengi mata melotot menyerang. Jelas ini tidak beres!
Sebagai seorang ibu, yang mengeram, menetek, mengelus, melahirkan, merawat, mendidik dan semua tetek bengek yang tidak dapat disebutkan satu persatu, singkatnya cinta! Saya yakin dengan kesimpulan itu.
Tetapi ikhtisar itu tidak cukup, saya tetap kewalahan karena belum menemukan pengertian, kenapa anak cikal ini, yang bakal berusia dua puluh tujuh tahun, begitu tampak kelimpungan belakangan waktu. Apa karena kebiasaan menyendiri dikamar? Belum lagi bekerja pasca mengundurkan diri? Atau karena para karibnya berada jauh dengan kediaman kami? Maklum, sejak Sekolah Menengah Pertama, ia selalu memilih luar kota.
Tetapi apa yang dapat dikata sekarang? Kini ia berada di Kampung Kota yang lirih ini. Tidak akan saya biarkan melulu berada di dalam kamar, maka dari itu, saya mengajaknya kemari, sebuah ruang publik, yang bakal mengadakan pameran tunggal dari perupa bernama Pablo Prabowo.
Jauh-jauh hari mendengar ajakan ini, ia acap kali memberi banyak alasan yang tidak dapat diterima oleh saya punya akal. Demi berharap ia datang untuk berbaur agar tidak menyendiri dan mengarah pada frustasi, saya membelikannya paket rias yang dibeli dari Dior dan Chanel. Dengan asa agar tampak percaya diri di dunia yang akrab betul dengan Dandyisme ini.
Dia anak perempuan saya satu-satunya, mempunyai dua adik laki-laki, satu tepat dibawahnya, akan segera menikah, sebab yakin akan kekasihnya bakal menjadi jodoh dunia akhirat.
Tetapi perempuan ini, tampak tidak akan pernah dapat mencintai seseorang kembali. Mungkin karena salah saya juga dulu, sempat mengusir laki-laki yang dibawanya ke rumah, lantaran penampilannya, bagi saya, begitu semrawut. Celana pendek berbahan jeans yang sengaja disobek, kemeja kumuh kedodoran, kepala gondrong diwarnai jambon, kulit kusam mengisyarat anti air. Siapa ibu yang rela memberikan anak gadisnya kepada manusia macam begitu? Saya, No!
Tetapi kini, saya tidak akan melarang apapun, karena beginilah dampaknya, ia menjadi begitu terlihat kacau dan bikin hati ini cemas. Apa karena sebab putus tali kasih dengan pacarnya? Tetapi bila ditanya, ia menghindar, dengan : “Bu, yang sudah, ya, biarlah sudah.”
Tetapi itu bukan jawaban yang membuat kecemasan lerai, melainkan semakin menanjak. Puncaknya pada satu minggu ke belakang, dengan kesepakatan bersama, saya membawanya ke Rumah Sakit Jiwa untuk diperiksa. Alhasil, bukan pungkas pada sembuh, ia malah kecanduan obat- obatan yang diberikan oleh dokter, seperti Antiansietas, Antidepresan, Antipsikotik, dan Antimania. Kadang kala, dengan mengelabui saya dan dokternya, ia menjual obat-obatan itu kepada kenalan dekatnya lewat aplikasi Telegram. Kacau!
Sebab menjanda, menjadikan tidak ada rekan berbagi keluh kisah, saya menceritakan parau ini kepada pamannya, adik langsung saya. Yang kini tengah saling berhadapan, dan menjadi penyelenggara dari kerja kebudayaan ini. Saya tidak peduli dengan seni, yang dalam pikiran hanya : “Anakku harus terlibat aktif pada ruang sosial. Berteman, bercanda, berkonflik untuk menemukan riangnya kembali. Senyumnya kembali!”.
Yes! Ia datang, hati saya benar riang. Tetapi ia tidak sedikitpun menyolek. Dari jauh, setiap orang yang mempunyai penglihatan, bakal menduga bahwa apa yang tengah ditatapnya tidak lain adalah seorang yang lagi mengalami gangguan jiwa. Saya yang sangat necis begitu malu, tetapi bagaimana pun ia adalah darah dagingku.
Tidak berselang lama, setelah anak saya duduk di atas kursi dan memain- mainkankan piano yang tersedia lantai bawah —Pameran di lantai atas.
“Hai, bestie!” Serta merta saya berteriak demikian, karena terkejut dibalut senang, juga hadir kangen, sebab melihat dengan jelas wajahnya, sobat kala dulu mondok di Tasik. Dia seorang yang jago betul membaca ayat-ayat Alquran. Ilmu qiraat dan tajwid-nya, sangat mantap. Ia teman sekamar yang selalu membuat saya minder. Tetapi itu dulu! Saya yakin, sekarang lebih mapan ketimbang dia dalam hal apapun. Lihat saja, saya ke sini memakai mobil pribadi, sedang dia menggunakan jasa ojek perempatan yang jaketnya sudah berubah warna dari kuning menjadi jingga.
Belakangan waktu, saya mendapat kabar dari beberapa teman, ia memilih hidup untuk menjadi guru mengaji anak-anak, remaja, dewasa, tidak terkecuali yang tua, yang baru mau mengenal alipbatasa. Semua itu gratis alias tidak meminta bayaran satu rupiahpun.
Itu jelas ketinggalan zaman, kiwari semua sudah bisa menjadi uang. Kenapa mengajar tidak sekalian dibikin konten saja? Diunggah di aplikasi TikTok sambil joged sedikit-sedikit?! Ah, saya yakin dia tidak akan paham dengan perkara- perkara digital. Lain dengan saya yang menggunakan iPhone lima belas ini.
Saya memperkenalkan buah hati yang sudah dapat berbuah ini kepada karib semasa mesantren. Keduanya berjabat tangan. “Aku juga punya anak seusia anakmu. Ia akan datang kemari. Aku pun ke sini ingin melihatnya membacakan naskah drama yang saban malam dilatihkan sambil teriak- teriak…..Nah, itu anak ku…”
Dari gerbang menuju kemari, saya memperhatikannya. Kurus tetapi tidak kering, tidak terlalu pendek, rambut lumayan rapih, mengenakan kemeja dengan dominasi warna magenta, dapat terbilang lumayan untuk jadi pemantik kehangatan dari putri saya yang sejak tadi menutup diri untuk saling berkontak dengan siapa pun, terlebih laki-laki.
Ia di sini kini, mencium tangan bundanya juga saya. Sedang kepada yang lain diberikan tos tangan. “Hai, boy, kenalin ini anak ibu.” Pendek dari saya. Pria ini memberi dua langkah maju, hendak mendekat kepada anak saya yang tak henti-henti memainkan piano. “Nanti saja, kenalannya, Bu. Kalau sudah selesai…” Saya mengangguk dibarengi syak wasangka, apakah laki-laki ini enggan sebab takut oleh penampilan dan sorot mata dari anak saya? Ah, lagi-lagi saya upaya akan gagal kembali!
“Hai, namaku…” Walau air mukanya culun, laki-laki ini ternyata berani untuk kembali mendekat guna mengulurkan tangan agar dapat bersalaman. Tetapi setitik pun tidak diberi hirau oleh anak saya. Yang dalam pikiran saya hanya : “Sudah berhenti wahai laki-laki, sebentar lagi dia bakal ngamuk, baginya upaya saling membuka diri adalah agresi.”
“Hai, kabel apa kabarmu?” Ujar laki-laki ini yang menghalau rasa malu sebab tertampik, dengan memegang kabel dan mengajak benda mati itu bicara. Aneh, anak saya terawa sedikit, bibirnya mengangkat ke atas, muncul senyum seperti tersipu. Kemudian berbalik, anak saya yang mengulurkan tangan : “Hilda!”
“Baik, Hilda. Namaku Misty…”
“Oh, kalo begitu namaku Erroll Garner!”
Keduanya tertawa terbahak, walau tak lama. Saya tidak mengerti, tetapi peduli setan. Tidak ada yang lebih bahagia bagi seorang ibu ketimbang tawa renyah dari anaknya.
“Kalo ini?” Tanya anak saya, ia kembali menekan-nekan tuts piano.
“Everything Happens To Me!” Keduanya lagi-lagi tertawa bersama, saya kembali turut gembira.
“You suka Chet Baker juga?” Ringkas dari anakku yang perlahan berani menengadahkan wajah.
“Tidak. Monk! Ada juga kan yang dilantunkan oleh Thelonious Monk…”
“Oh, begitu? I kira Paul Desmond saja yang pernah menggubah itu…”
“Tidak ada gubahan, jazz selalu baru, jazz selalu personal, jazz milik semua orang. Bahkan untukku yang bego ini!” laki ini tertawa kering, saya merasa gelak itu dibuat-duat. Anak saya bertanya kembali dengan melantunkan nada-nada dari alat musik tuts : “Kalau ini?” Serta merta laki-laki ini meloncat menuju atas kursi, gayanya seperti seorang vokalis, berteriak kencang : “Modern Bob!!” Keduanya sama-sama terpingkal.
Kami, terutama saya, yang melihat cara mereka bercakap, tidak sampai pada mengerti. Tetapi saya turut girang dan sedikit terbahak sebab melihat gestur laki-laki ini, begitu mirip cacing kepanasan.
“I jadi ingin potong rambut…” Kembali dari anak saya. Laki-laki itu berjalan menuju depan untuk saling berhadapan, kemudian : “Kamu cocok dipapak pendek. Eh, kamu suka kalau rambut kamu dikriwil-kriwil?”
“Enggak!”
“Tapi kamu pasti bagus…”
“Itu karena you suka…”
“Memang aku suka!”
“Tetapi kata sahabat I bakalan jelek. I dulu sempat ingin, tapi urung…”
“Dalam hal ini, kamu mesti memilih. Mau dengar aku atau sahabatmu...”
“Bagaimana I bisa percaya you, kita belum bercakap lebih dari tiga puluh menit…”
“Tetapi dalam rambut aku pasti menang ketimbang sahabat kamu itu!”
“Kesimpulan dari mana itu?”
“Coba beri tahu siapa nama sahabatmu itu…”
“Zahra…”
“Dia kalo bangun tidur pasti bakal buka mata, ngucek muka kemudian baca doa. Setelah itu pergi ke kamar mandi. Kalo aku lain lagi!”
“???”
“Aku kalau bangun tidur, kucek muka, baca Hairstyle Magazine. ckckckck” Dilanjutkan dengan : “Kalo mau potong, aku anter sekarang!”
“Tengok, sudah jam sembilan malam!”
“Pangkas rambut tempat biasa aku potong, masih buka, kok…”
“Itu kan untuk cowo…”
“Apa bedanya? Ini hanya perkara memotong rambut di kepala!!”
“Ah, you tidak mengerti. Tetapi I bakal coba dikeritingkan ini rambut. Besok tolong antar ke salon…”
“Oke, beri aku alamat kamu!” laki-laki ini membuka tas selempangnya, menyobekan kertas dan membawa bolpoin. Menyodorkan.
“Kuno banget! Kenapa mesti tulis-tulis segala, you merasa diri pangeran Inggris yang bakal kirim surat lewat merpati, begitu?”
“Bukan begitu. Aku suka dengan segala upaya. Untuk sampai pada alamat, lebih asik bila aku mencari-cari dulu. Sebelum bertemu perlu berkeringat dulu, kesal dulu, dumel dulu, nyasar dulu, kemudian bertemu dan segalanya menjadi tuntas! Hal-hal yang aku rindukan, yang sulit ditemukan di dunia kita sekarang. Tinggal kirim google maps, kirim foto atau video, langsung sampai. Ah, kita terlalu jauh bagi perasaan yang menarik-narik…”
“Nomor Whatsapp saja, oke?”
“Baiklah, ini hanya untuk efektifitas saja, kan? Bukan buat kirim-kirim pesan cengeng…” Laki-laki melanjutkan dengan mengarahkan kepada diri sendiri, tetapi semua orang mendengar “Langsung video call saja sambil sleep call. Oke?!”
Anak saya nyengir, macam sapi sedang tebar pesona : “Husss…Jangan terburu-buru. Voice Note dulu…”
“Alah, Voice Note itu memberi jeda, ada stilistika omongan disana…”
Bising terdengar pengeras suara yang mulai dibunyikan. Mengganggu perhatian saya. “Cek, cek, cek. Oke untuk penutup agenda ini, kita persilakan Faslah Lima Musadek untuk membacakan beberapa sajak yang telah beliau tulis…”
Tanpa tedeng aling-aling, anak laki-laki dari bestie saya naik menuju ruang berlampu itu. Tidak berteriak, agak lirih, sedikit parau, lumayan bersemangat, tampak malas : “Kalau saya tidak bisa bertemu denganmu, biarkan saya menulis ini. Kamu tahu, ini akan menjadi asap yang merangsek masuk pada kamarmu! Lalu aku akan melamun kembali, menangisi hari- hari. Kapan kita bisa berkencan?!”