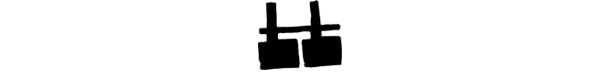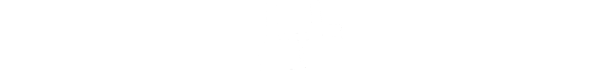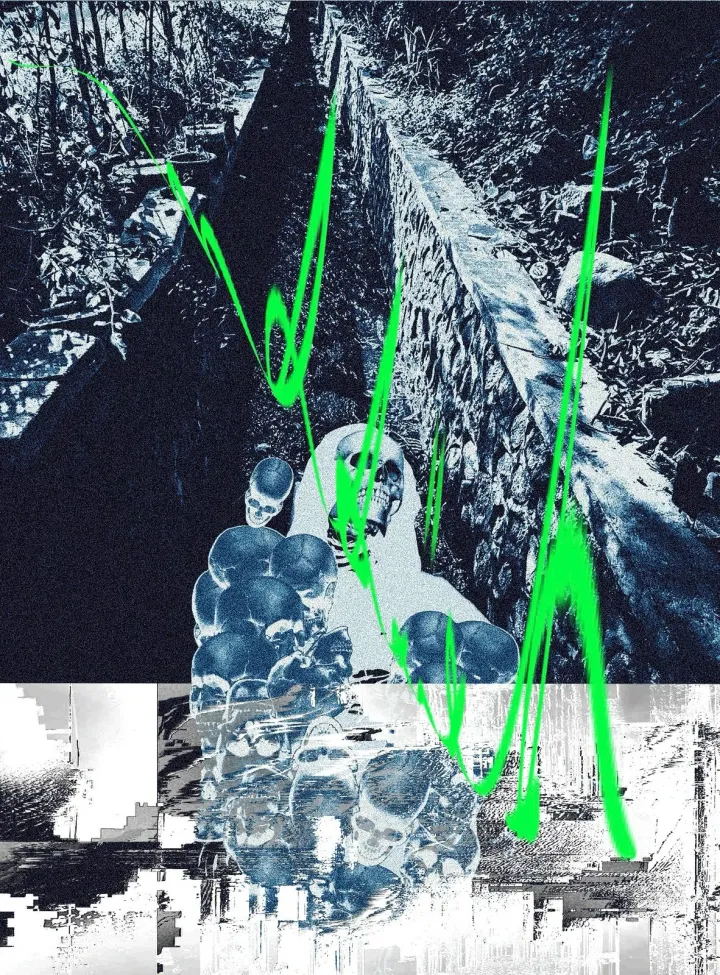Hari itu akhir pekan, aku lupa hari apa karena sudah cukup lama aku menganggur. “Ternyata bosku tidak peduli dengan mimpiku, Ia hanya peduli dengan hasratnya sendiri dan mengelabuiku dengan janji delusif tentang nilai–nilai ideal yang sering ia muntahkan ke wajahku saat aku mengerjakan patung yang menghasilkan puluhan juta rupiah ke dalam kantong celananya.”
Itu aku katakan kepada temanku, Ivan. Ketika kami sedang menggambar di kamar kostnya. Aku menggambar sepatu–sepatu yang berkerumun di pojok ruang kamarnya, sedang Ivan menggambar sebuah gelas kayu yang bersandar pada botol beling; katanya ia melihat sesuatu yang romantik dari interaksi antara dua benda yang ia gambar itu.
Ivan menanggapi perkataanku sembari menggambar “ngomong-ngomong soal pekerjaan, aku jadi ingat salah satu puisi yang kau tulis, ‘apakah sarapan bubur setengah jam sebelum bekerja dapat membuat aku masuk surga?’ aku berpikir jika aku memilih untuk sarapan sebelum bekerja, maka aku akan masuk neraka; ya, neraka keterlambatanku datang ke tempat kerja dan menghadapi ribuan ludah yang bosku tembakkan ke wajahku.”
“Mengapa kau bisa berpikir seperti itu? Sebetulnya aku menulis puisi itu karena setiap aku berangkat kerja aku selalu sarapan bubur di jalan Karapitan, harganya hanya lima ribu rupiah ditambah rasanya cocok denganku dan jarak dari jalan Karapitan ke tempat kerjaku hanya setengah jam; dengan itu, ketika aku memutuskan untuk mengulangi sarapan bubur setengah jam sebelum bekerja, aku bisa menghendaki sebuah perulangan yang bisa membuat aku merasakan surga dalam siklus perulangan tersebut nantinya.” Jawabku pada Ivan.
“Sialan, kenapa aku memikirkan neraka dari puisimu yang mengharapkan surga ya?” Kata Ivan sambil tertawa. Aku menanggapi lagi Ivan, “Tetapi karena sekarang aku sudah tidak bekerja dan jelas aku juga tidak sarapan bubur, apakah aku masih bisa masuk surga?” Ivan langsung menanggapi pertanyaanku. “Bukan begitu pertanyaannya, harusnya: apakah tidak bekerja sekaligus tidak sarapan bubur bisa membuat kau masuk neraka?” Aku tertawa terbahak-bahak karena pertanyaan Ivan tersebut.
Kemudian kami melanjutkan kegiatan menggambar kami, gambarku sudah hampir rampung, pun gambar milik Ivan. Sebelum Ivan menggoreskan beberapa goresan terakhir pada permukaan kertas untuk merampungkan gambarnya, ia kembali membuka percakapan. “Aku pikir aku akan berhenti bekerja. Agar aku bisa memikirkan surga alih–alih memikirkan neraka yang ternyata adalah tempatku bekerja selama ini.” Kemudian ia menempelkan gambarnya itu di tembok kamarnya yang berwarna abu-abu. Aku termenung mendengar apa yang Ivan katakan, gambarku rampung dan ku simpan di depan kami berdua, aku hendak membawanya nanti jika aku pulang. Lalu kami berpikir untuk membeli sebotol arak bali; obrolan kami terhenti ketika adzan awal berkumandang.