Rona Merah
Sebuah lakon monolog.
Latar panggung seperti berada di sebuah kafe, memiliki satu kursi dan meja tunggal, tetapi ada latar jeruji besi di belakang. Lampu remang-remang, ada satu properti lilin kecil di atas meja. Keadaan baru masuk waktu senja. Aktor duduk di kursi sambil menopang dagu di atas meja dan kakinya menggantung karena tak sampai ke lantai. Kostum menggunakan dress putih dengan noda merah di bagian bawah, model tahun 1930-an dengan rambut digerai, tanpa alas kaki.
Tuk... Tuk... Tuk... (tangan satunya yang bebas mengetuk-ngetuk meja belajar, tiba-tiba tersenyum).
Boleh jadi... Ah aku tidak ingin membayangkannya. Kalian pernah punya seorang yang disukai? Aku punya. Dia seorang pria yang baik, matanya besar, kulitnya sawo matang, tingginya standar seorang laki-laki berumur 25-an.
Bicaranya lembut, perhatian, pemberani, dan sangat kucintai. Pertama dan terakhir bertemu di tempat ini. Benar, tempat ini. Mau kuceritakan? Sebentar… (membenarkan duduknya) Kuingat, waktu itu aku sedang sendirian duduk di sini. Aku kabur dari rumah hari itu.
Nanti aku ceritakan kenapa, sekarang fokus padanya dulu. Hendak pulang, ternyata hujan turun deras sekali. Tak mau terguyur dan berakhir harus demam 3 hari lebih baik aku tinggal lebih lama. Toh aku memang kabur dari rumah dan tidak perlu buru-buru kembali, kan? Saat akan kembali ke dalam, seseorang berdiri di belakangku sambil memandang hujan ke luar. Tingginya 30 cm di atasku. Aku harus mengadah mencari wajahnya. (tersenyum) Tampan, batinku.
Tiba-tiba saja dia bersuara, “Mau kuantar pulang, Nona? Tapi aku tidak membawa kendaraan”, ucapnya. “Lalu dengan apa kau akan mengantarku?” tanyaku. “Naik bus? Keberatan?” Jawabnya. Aku sedikit takut waktu itu, namanya perempuan harus mempunyai rasa curiga pada laki-laki. Mereka itu buaya, bukan, serigala. Siapa tahu niatnya buruk kan tidak tertulis di atas jidatnya. Waktu itu aku tidak menjawabnya dan kembali duduk di sini.
Aku pesan minuman lagi supaya tidak diusir jika hanya duduk diam saja. Pesananku datang dibawa oleh laki-laki tadi, aneh, kan dia bukan pelayan di sini. Kutanya apa maunya dengan wajah kugarangkan supaya dia terintimidasi oleh wajahku. Dia malah memamerkan senyum manisnya dan duduk di sana (menunjuk kursi di depannya). “Boleh saya berkenalan dengan Nona?” chh, pesonaku memang tidak bisa diragukan lagi. Aku memalingkan wajahku ke mana pun asal bukan padanya. Lagi-lagi dia pamer senyum manisnya.
(membayangkan saat duduk bersamanya) Kami berbicara cukup lama sore itu. Kuperhatikan, dia terlalu sempurna. Wajahnya, tubuhnya, sikapnya, cara dia bicara dan tertawa. Karena kami sudah cukup akrab, dan aku penasaran pada bentuk dia yang sempurna itu akhirnya aku tanya, “Tuan, maaf sebelumnya, tapi apakah kau pernah mendengar bahwa kau begitu sempurna?”
Dia menjawab, “Tidak, Nona. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Semua orang punya sesuatu yang mereka sembunyikan, bisa jadi kekurangan yang tidak ingin ketahuan oleh orang lain.” Aku memiringkan kepalaku dan bertanya sekali lagi, “Benarkah? Lantas, apa yang menjadi kekurangan Tuan?” Gila aku, dia terus saja memamerkan senyum manisnya. Dia menjawab dengan serius tanpa memutus pandangan denganku. “Nona, aku selalu menjadi pelupa saat bertatapan dengan orang cantik, biasanya aku akan mengulangi ucapanku.” Lalu aku hanya menatapnya tak sabar, “Lalu bagaimana? Apa yang terjadi?” Ia menarik nafas “Nona, aku selalu menjadi pelupa saat bertatapan dengan orang cantik, biasanya aku akan mengulangi ucapanku.” Aku mengerutkan keningku, “Lalu?” Lagi dia bilang “Nona, aku selalu menjadi pelupa saat bertatapan dengan orang cantik, biasanya aku akan mengulangi ucapanku.”
(menutup wajahnya malu). Saat itu wajahku panas, rasanya seperti terbakar. Benar, bisa gila aku kalau terus-terusan berbicara dengannya. Saat aku merasa senang berbicara dengannya, tiba-tiba…
Tiba-tiba ada tangan yang meremas bahuku.
Rasanya tak asing.
(meringis ketakutan) Jangan sekarang…
Aku membalikan tubuhku dan melihat ada sosok lelaki tua di sana.
(penuh kebencian) Oh, ayah tiriku, tetapi tak sudi aku panggil dia dengan sopan. Dia terlalu hina untuk mendapat panggilan itu. Si tua, orang itu terus meremas bahuku dengan keras. Aku tak kesakitan, sudah kebal, sudah biasa aku diperlakukan begitu. Namun, satu hal yang tidak biasa adalah ada orang yang membelaku. Laki-laki itu menghempaskan tangan milik si tua itu sampai lepas dari bahuku, dia berkata dengan tegas padanya, “Jangan sentuh dia, atau aku potong pergelangan tanganmu.”
(tertawa) Sesuatu menggelitik perutku.
Laki-laki itu kemudian meraih tanganku dan mengajakku untuk pergi dari sini. Namun, si tua itu tak kalah cepat, ia meraih kakiku dan membuatku jatuh dari kursi ini. Seperti ini (menjatuhkan diri dari kursi). Ia menekan perutku keras sekali (kesakitan sambil memegangi perut), kemudian naik ke leher dan mencekikku dengan kuat (mencekik dirinya sendiri).
Mataku berkunang-kunang. Ak… Aku… Kehabisan nafas… Nafas…
Satu… Dua… Tiga… Sepertinya aku akan mati, tetapi tidak. Si tua itu terlempar ke belakang sampai kepalanya mengenai vas bunga keramik yang ada di pojok sana (menunjuk). Laki-laki itu langsung menolongku, merapalkan kata-kata baik, supaya aku tidak kehilangan fokus dan tetap mengatur nafas.
Tarik nafas… buang… tarik nafas… buang…
(kembali terduduk santai) Aku mulai tenang. Mataku sudah tidak berkunang-kunang lagi dan nafasku sudah teratur. Aku menatap matanya dalam. Kulihat ada ketulusan, terlihat khawatir pun ada, tetapi aku tak yakin karena tak sempat aku bertanya… lantaran… lagi-lagi dia tersenyum manis.
Dasar tukang pamer (tersipu)
Aku ikut tersenyum karenanya. Lucu bukan? Sepertinya aku jatuh cinta padanya. Aku sudah membayangkan betapa akan bahagia hidupku jika bersamanya, hari-hari penuh canda tawa, aku disayanginya, dijaganya, dan dianggap berharga. Itulah isi kepalaku sampai saat ini.
Namun, apa yang terjadi? Saat kami akan bangkit, tiba-tiba saja sebuah dentuman keras menyerang telingaku.
DOR…!
Laki-laki itu kembali terduduk dan jatuh ke pangkuanku.
Aku kira dia begitu karena kaget sepertiku.
Eey, satu kekurangannya aku temukan juga akhirnya. Dia adalah laki-laki penakut, pada suara keras saja dia takut.
“Bangun, kau ini seperti anak kecil.” Ucapku padanya.
Dia sama sekali tak bergerak.
Aku masih tersenyum melihatnya tertidur di pangkuanku. Terus saja aku membangunkannya. Namun, ia tidak kunjung bergerak. Tiba-tiba saja baju putih bersih kesayanganku ini berubah warna jadi merah. Aku hampir memukulnya dan berniat untuk memarahi laki-laki itu karena kupikir dia memuntahkan jus stroberi miliknya.
Namun, saat aku angkat kepalanya, tiba-tiba terbentuk sebuah lubang di jidatnya.
Dari sana keluar banyak darah segar yang kelihatannya tidak akan berhenti begitu saja.
Kulihat si tua dibelakangnya, ia sedang memegang senapan ayam liar sambil mematung tak bergerak. Entah kenapa dia. Kurasa dia menyesali perbuatannya. Dia perlahan mundur dengan langkah kecil dan terseret. Senapannya ia jatuhkan dengan lemas dari genggamannya. Aku yang saat itu sudah sangat marah segera berdiri dan mencapai senapan itu (berdiri dengan penuh rasa marah), aku pompa dan—DOR…!
Aku membidik kakinya.
DOR…!
Lalu perutnya.
DOR…!
Terakhir kepalanya.
(menarik nafas dalam dan kembali duduk di tempat semula dengan tatapan kosong) Begitulah kukira. Ceritaku dan rona merah pada baju ini.
Sudah sekitar 3 tahun mungkin, aku tidak pernah mengganti pakaianku. Padahal orang-orang cerewet itu selalu memaksaku untuk berganti baju, tentu saja aku tidak mau.
Oh, aku juga tidak pernah mau mencuci ini. Ini adalah baju favoritku. Bau laki-laki itu… Baunya masih bisa kucium dari pakaian ini. Aku suka… Aku suka sekali (berjalan ke tengah dengan tatapan yang semakin kosong).
Pada rona merah yang selalu dia berikan. Entah pada pipiku… atau pada bajuku.
Selesai.
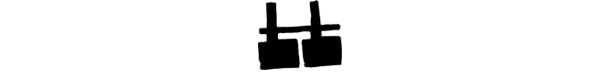
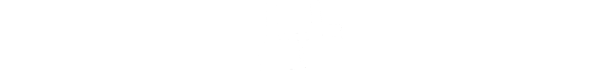


Comments ()