Saya lahir dan besar di Jakarta, sebelum akhirnya merantau ke Bandung untuk menuntut ilmu di salah satu institusi seni. Meski berbeda kota, pengalaman ruang yang saya alami pada kedua tempat ini tidak jauh berbeda. Lanskap urban pada dua tempat ini erat dengan arus perdagangan dan komersialisasi yang dipenuhi dengan nuansa keterasingan. Hal ini membentuk pengalaman keseharian yang serupa di tengah hiruk-pikuk kota. Bagi Georg Simmel, pada Zerzan, kota tak hanya memberikan sensasi kesepian, kota juga menawarkan kematian rasa yang memperkeruh suasana kota.
Alienasi sudah hadir semenjak munculnya struktur kekuasaan yang terinstitusionalisasikan. Resistensi terhadap alienasi pun menjadi sama tuanya, karena sedari dulu setiap ada struktur kekuasaan pasti akan ada tatanan masyarakat yang tidak ingin dikontrol oleh otoritas yang berkuasa. Namun, kontrol sosial yang sudah terlalu mutakhir ini tidak dapat meninggalkan sedikit ruang untuk melawan. Menurut Marx, terjadinya alienasi karena adanya pemisahan antara kelas pekerja dan hubungan produksi yang menghasilkan keterasingan bagi pekerja melalui konsep properti pribadi. Apa yang dihasilkan para pekerja mungkin membuahi banyak hal indah, tetapi tidak untuk pekerjanya itu sendiri. Dalam manuskrip Marx berjudul Economic-Philosophical Manuscript (1844), keterasingan kelas pekerja dijelaskan melalui kausalitas paradoksal; semakin banyak pekerja berproduksi, semakin besar nilai yang dihasilkan—semakin tak bernilai dirinya sendiri; semakin meningkat kualitas produknya, semakin ia terpinggirkan; semakin kuat fisiknya, semakin lemah posisinya; semakin mahir pekerja, semakin ia diperbudak oleh sistem yang membuatnya terasingkan. Dengan kondisi seperti ini, kesadaran terhadap perubahan sosial akan semakin terkikis, terus membuat jarak yang melintang antara pekerja dengan kehidupannya.
Arsip selalu menjadi alat yang dapat digunakan untuk memahami dan merakit identitas mereka terhadap ruang yang kerap kali terasa tidak akrab. Arsip berfungsi sebagai jembatan antara pengalaman partikular dan lanskap sosial. Menurut Assmann, arsip tidak hanya menyimpan fakta-fakta sejarah, tetapi memiliki peran penting dalam membentuk narasi, identitas, dan makna yang diterima oleh masyarakat. Arsip memungkinkan kita membaca ulang konteks ruang serta menjadikannya pijakan untuk memahami konteks-konteks yang lebih luas.
Esai ini berupaya merefleksikan, bagaimana kapitalisme memengaruhi identitas masyarakat yang mengalami keterasingan kota melalui otomatisasi arsip dan media digital. Praktik ini seiring dengan kebiasaan dokumentasi sehari-hari masyarakat, seperti unggahan di media sosial, rekaman aktivitas, hingga distribusi data yang disebar luaskan melalui sistem algoritma media sosial. Namun, praktik pengarsipan dalam konteks ini bukan sebagai catatan netral, melainkan alat yang digunakan kapitalisme untuk mengonstruksi dan mereproduksi identitas masyarakat.
Menyimpan dan Merawat Memori Kolektif
Berdasarkan pemikiran Assmann dalam karya Salerno dan Rigney yang berjudul Archiving Activism in The Digital Age (2024), arsip selalu terkait dengan konsep memori. Arsip dibangun atas informasi yang dipilih karena dianggap cukup penting untuk dipertahankan. Salerno dan Rigney juga menjelaskan bahwa dalam studi gerakan sosial, arsip hampir tidak pernah dianggap sebagai media transmisi memori lintas generasi. Arsip justru memiliki padanan konsep ‘repertoar’ yang terdiri dari model-model interaksi yang diwariskan melalui praktik yang terwujud dalam tubuh. Praktik ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan akan praktik tersebut dapat diteruskan sepanjang waktu dalam suatu gerakan sosial. Dalam Memory in a Global Age (2010), Assmann menjelaskan distingsi antara 'memori personal' dan 'memori kolektif'. Dalam memori kolektif, terdapat tiga aspek utama yang disebut sebagai; memori komunikatif, budaya, dan politik. Memori komunikatif berkaitan dengan komunikasi sosial seperti kesadaran dalam memperoleh suatu bahasa. Memori budaya adalah bentuk eksternalisasi dari memori yang bersifat personal maupun komunikatif. Hal ini dapat ditemukan dalam simbol-simbol seperti teks dan gambar di berbagai lieu de mémoire seperti museum, monumen, atau bahkan barang mantan sekalipun. Arsip menjadi salah satu instrumen penting dalam merakit memori budaya. Memori budaya berkembang selama berabad-abad melalui interaksi tiap entitas yang tidak terkontrol dan tumbuh secara mandiri dari ‘bawah-ke-atas’. Arsip berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pengorganisasian ingatan kolektif yang memungkinkan masyarakat memiliki rujukan pada peristiwa dan interaksi yang telah tumbuh kembang.
Sementara itu, memori politik memiliki karakter eksternal dan simbolis yang sama dengan memori budaya, tetapi ia menjadi memori yang diinstitusikan dari ‘atas-ke-bawah’—tergantung organisasi politik apa yang menginstitusikannya. Bagi Salerno dan Rigney, terminologi dari distingsi memori yang diteorikan oleh Assmann, sedikit berubah seiring waktu. Namun, pendekatannya tetap didasarkan pada perbedaan antara bentuk memori pasif dan aktif—di mana ‘memori aktif’ terkait dengan narasi yang menjalar, dan ‘memori pasif’ berhubungan dengan narasi yang disimpan. Assmann mengatakan bahwa memori adalah sistem yang terbuka. Namun, memori tidak sepenuhnya terbuka dan meluas tanpa batasan. Terdapat banyak tumpang tindih di antara bentuk-bentuk memori-memori tersebut—terutama yang berkaitan dengan identitas. Setiap individu memiliki berbagai identitas sesuai dengan kelompok, agama, dan ideologi yang mereka yakini. Assmann menambahkan bahwa memori adalah pengetahuan yang memiliki indeks identitas—pengetahuan tentang diri sendiri, sebuah identitas diakronis—baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari keluarga, generasi, kelompok, atau suatu agama.
Dalam kehidupan sehari-hari kita, arsip berfungsi lebih dari sekadar tempat penyimpanan informasi saja. Ia dapat menjadi instrumen yang menghubungkan pengalaman individu dengan konstruksi memori kolektif. Setiap catatan dan dokumentasi berpotensi untuk menyatukan pengalaman personal dengan narasi yang lebih besar. Lalu, memori apa yang dapat disimpan dan dirawat oleh masyarakat yang mengalami keterasingan kota? Kondisi keterasingan kota menciptakan kontradiksi antara pengalaman personal dengan memori yang disimpan, sehingga memori yang terbentuk bukan lagi hasil interaksi sosial yang organik dan autentik—melainkan tumpang tindih memori kolektif yang telah diproduksi dan dikontrol oleh sistem kapitalisme.
Catatan Digital dan Konsumerisme
Manusia secara sadar atau tidak, selalu mencatat dan menyimpan banyak hal dalam kehidupan sehari-harinya. Kita diperkenalkan dengan kegiatan mencatat saat kita sekolah dasar, di mana para murid diwajibkan mencatat materi pelajaran sebagai tugas maupun untuk catatan pribadi. Kebiasaan ini mengasah pola pikir bahwa pencatatan adalah cara untuk menyimpan dan mengolah informasi. Dengan aktivitas pencatatan, para murid dapat mengerti akan peran dokumentasi dalam membangun pemahaman atas pengetahuan. Kebiasaan mencatat yang lebih personal dapat kita temukan melalui buku harian atau diary. Berbeda dengan mencatat materi pelajaran, buku harian kerap diisi oleh perasaan penulis terhadap pengalamannya. Penulisan akan angan, sensasi, atau bahkan umpatan selalu memberikan sensasi katarsis tersendiri bagi penulisnya. Proses ini menciptakan ruang refleksi yang intim, di mana perasaan dapat dituangkan tanpa intervensi eksternal. Memang terdengar klise, tetapi hal ini memberi semacam “ruang aman” bagi individu yang menuliskan buku hariannya.
Di era digital dewasa ini, cara kita mencatat dan mengarsipkan pengalaman telah bertransformasi bersamaan dengan perkembangan teknologi. Banyak orang yang dulu menggunakan buku fisik untuk mencatat, sekarang beralih ke ponsel pintar. Ponsel pintar menawarkan berbagai fitur yang jauh lebih praktis dan efisien. Sedangkan, buku fisik terbatas pada kapasitas halamannya yang kini tergantikan oleh penyimpanan awan atau server yang hampir tak terbatas. Salah satu fenomena yang muncul dalam 2 dekade terakhir adalah bagaimana masyarakat dapat menggunakan media sosial sebagai wadah untuk mendokumentasikan kehidupannya. Fitur otomatisasi arsip yang diberikan platform media sosial menjadi salah satu fasilitas yang diberikan untuk pengguna dalam menyimpan banyak momen di hidupnya. Pengguna media sosial sering kali membagikan status, foto, atau video, yang mencatat peristiwa hidup mereka dalam format yang mudah diakses dan dikelola. Fasilitas seperti Like, Comment, dan Share menciptakan interaksi dan partisipasi masyarakat menjadi lebih dinamis. Secara keseluruhan, media sosial telah menjadi salah satu sarana bagi masyarakat modern dalam mengarsipkan kehidupan mereka.
Di sisi lain, media sosial seperti Instagram dan Tiktok sering kali menonjolkan citra dan simbol sosial yang kuat dalam mempengaruhi persepsi kita terhadap diri serta orang lain. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi tempat berbagi dan berpartisipasi, tetapi juga ruang di mana identitas dinilai berdasarkan simbolisme dan citra dapat ditampilkan. Dalam kerangka masyarakat konsumsi yang diterangkan Baudrillard, nilai-nilai, identitas, bahkan realitas itu sendiri seringkali terbentuk melalui apa yang kita konsumsi. Baudrillard memandang bahwa konsumsi tidak hanya tentang memperoleh barang materi, tetapi juga proses di mana kita memperoleh simbol, citra, dan pengalaman yang berhubungan dengan objek tersebut. Dalam konteks ini, produk dan barang dipandang sebagai simbol dari status, identitas, atau kepuasan psikologis. Hal ini berhubungan dengan pernyataan Fuchs pada karya Social Media a Critical Introduction (2014), di mana media sosial menjadi tempat utama masyarakat membentuk representasi dari kehidupan mereka sendiri. Konsumen media sosial adalah objek komodifikasi ganda—mereka sendiri menjadi komoditas—dan melalui komodifikasi ini kesadaran mereka secara permanen terpapar pada logika komoditas dalam bentuk iklan.
Media sosial menjadi media baru untuk masyarakat kota dalam membentuk identitas dalam keterasingannya. Arsip masyarakat kota cenderung merekam pengalaman yang telah terfragmentasi dan tersegmentasi—di mana identitas digantikan oleh narasi yang dibentuk oleh ekonomi pasar dan struktur kekuasaan. Memori yang tersimpan dalam arsip masyarakat kota lebih sering berupa rekaman-rekaman kehidupan yang telah dikomodifikasi. Dalam konteks ini, kapitalisme sebagai sistem produksi tidak hanya mempengaruhi cara manusia bekerja, tetapi juga cara kita mengingat. Identitas bukan lagi hasil dari hubungan sosial yang dinamis, tetapi sekadar konstruksi sosial yang diproses oleh mekanisme pasar. Dengan demikian, media sosial menjadi sebuah arena di mana memori diperebutkan, dibentuk, dan dikaburkan oleh sistem yang menciptakan keterasingan itu sendiri. Baudrillard mengatakan, masyarakat yang memperoleh kepuasan dari respons dan interaksi yang mereka terima pada media sosial akan menciptakan siklus “haus” yang tidak pernah terpuaskan. Pencarian akan apresiasi, pengakuan, pada platform media sosial dapat menjadi bagian dari konsumsi yang terus-menerus dalam upaya untuk mempertahankan citra yang tercipta. Secara tidak sadar, ingatan kita terhadap diri kita dan keterasingan sudah terperangkap dalam tatanan yang dieksploitasi oleh sistem kapitalisme—seperti sebuah perjanjian iblis yang menghisap jiwa kita. Kapitalisme tidak hanya mengawasi, tetapi juga memonopoli arsip dan memori kolektif kita—menjadikan identitas kita sepenuhnya terintegrasi dalam poros ekonomi pasar. Ketergantungan kita terhadap hal ini mengharuskan kita untuk merefleksikan kembali secara kritis, bagaimana kita terus-menerus dieksploitasi oleh kapitalisme tanpa ada jalan keluar yang konkret.
Kapitalisme memegang kendali atas arsip dan memori kolektif kita, menjadi sebuah ironi yang menggambarkan bagaimana sistem ini membelenggu kita dalam keterikatan yang mustahil untuk dilepaskan. Setiap upaya untuk melepaskan diri selalu dibayangi oleh ancaman kehilangan jejak dan identitas yang sudah tertanam dalam struktur kapital. Sebagai penutup, saya ingin mengutip peringatan yang selalu muncul ketika seseorang ingin meninggalkan permainan.
“Are you sure you want to quit? All unsaved progress will be lost”
Daftar Pustaka
Zerzan, John, 2008, Alone Together: The City and its Inmates, Diakses dari https://theanarchistlibrary.org/library/john-zerzan-the-mass-psychology-of-misery
Abacus, Killing King, 2001, Where Do We Meet Face to Face? Diakses dari https://theanarchistlibrary.org/library/killing-king-abacus-where-do-we-meet-face-to-face
Marx, Karl, 1844, Economic-Philosophical Manuscript, 1844: Enstrange Labour, diakses dari https://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/manuscripts/labour.htm
Baudrillard, Jean (1994). Simulacra and Simulation (Sheila Faila Graser, terjemahan berbahasa inggris). The University of Michigan Press
Fuchs, Christian (2014). Social Media a Critical Introduction, Sage Publications
Salerno, Daniele, Rigney, Ann, dll, 2024: Archiving Activism in The Digital Age, Institute of Network Culture.
Assmann, Aleida, Conrad, Sebastian, 2010: Memory in a Global Age: Discourses, Practices and Trajectories, Palgrave Macmillan.
Grochowski, Konrad, Breiter, Michael, dll, 2020: Introduction to Data Science and Machine Learning, Serialization in Object-Oriented Programming Languages, Intechopen. Diakses dari https://www.intechopen.com/chapters/68840
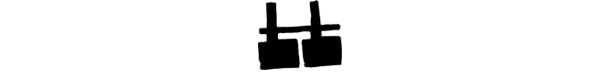
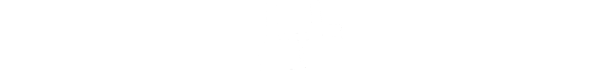

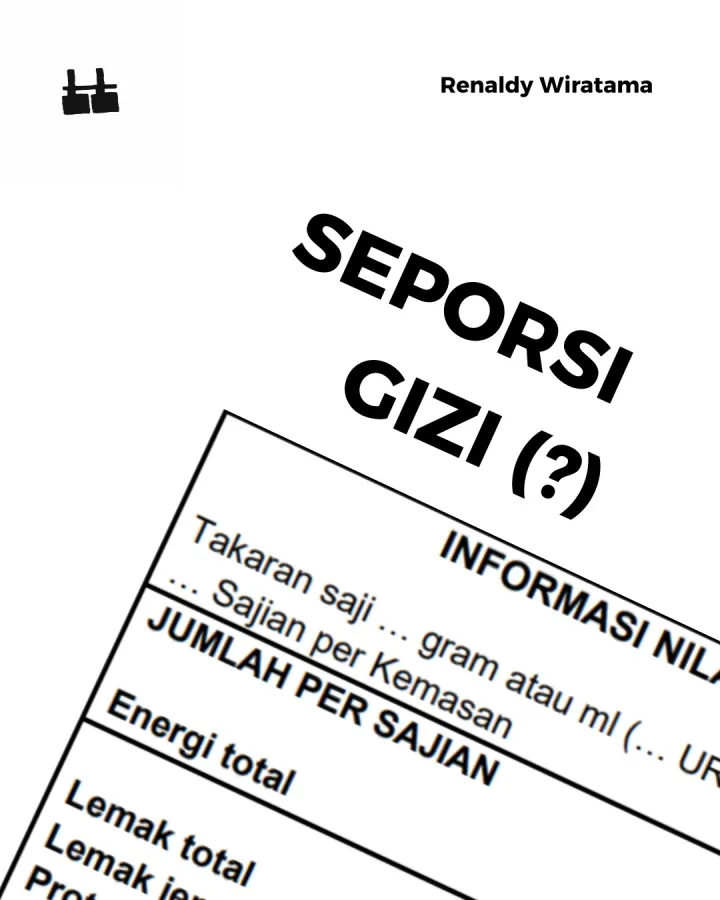
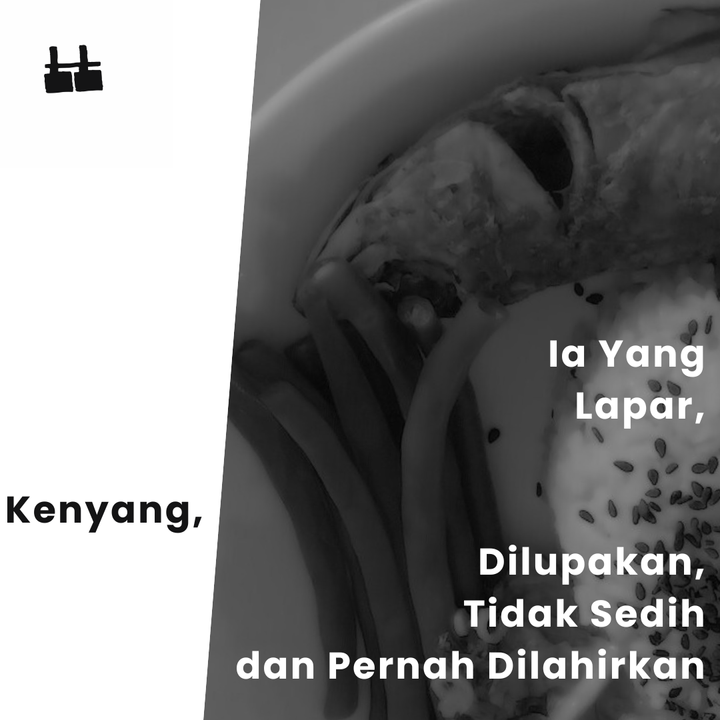
Comments ()