Ketika Anggaran Menjadi Cermin Nurani
Di banyak organisasi—kampus, perusahaan, bahkan keluarga—anggaran sering dipahami sebagai urusan angka belaka. Ia dianggap netral, teknis, dan dingin. Padahal, di balik setiap keputusan anggaran, tersembunyi pilihan nilai: siapa yang diprioritaskan, apa yang dianggap penting, dan ke arah mana masa depan diarahkan. Anggaran, dengan demikian, bukan sekadar instrumen manajemen; ia adalah cermin nurani.
Dalam filsafat, khususnya etika praktis, tindakan manusia selalu diasumsikan bermuatan nilai. Aristoteles menyebut praxis sebagai tindakan yang mengandung tujuan moral, bukan sekadar menghasilkan sesuatu (poiesis). Jika kita tarik ke dunia keuangan, maka penyusunan anggaran bukan hanya soal efisiensi, melainkan juga soal telos: untuk apa uang itu digunakan, dan manusia macam apa yang hendak dibentuk olehnya.
Masalahnya, logika keuangan modern kerap terjebak pada rasionalitas sempit. Efisiensi diukur semata-mata dari penghematan biaya, bukan dari dampak kemanusiaan. Akibatnya, pemotongan anggaran sering dilakukan tanpa refleksi etis: kesejahteraan karyawan dikorbankan, kualitas pendidikan diturunkan, atau pelayanan publik disederhanakan hingga kehilangan martabatnya. Di titik ini, manajemen keuangan berubah menjadi mekanisme kekuasaan yang tak lagi peka.
Filsuf Emmanuel Levinas mengingatkan bahwa etika lahir dari perjumpaan dengan yang-lain. Wajah orang lain memanggil kita untuk bertanggung jawab. Dalam konteks anggaran, “wajah” itu bisa berupa dosen honorer yang menggantungkan hidup pada honor kecil, mahasiswa yang kesulitan membayar biaya studi, atau masyarakat kecil yang terdampak kebijakan fiskal. Anggaran yang etis adalah anggaran yang bersedia berhenti sejenak untuk “melihat wajah” mereka.
Namun, etika bukan berarti meniadakan rasionalitas. Manajemen keuangan tetap membutuhkan disiplin, akuntabilitas, dan perencanaan yang ketat. Justru di sinilah kebijaksanaan (phronesis) bekerja: kemampuan untuk menimbang secara proporsional antara keberlanjutan finansial dan tanggung jawab moral. Anggaran yang bijaksana tidak boros, tetapi juga tidak kejam.
Dalam praktik, ini berarti menggeser paradigma dari cost-centered ke value-centered budgeting. Pertanyaannya bukan hanya “berapa yang bisa dihemat?”, melainkan “nilai apa yang sedang kita rawat?”. Transparansi, keadilan, dan keberpihakan pada yang lemah bukanlah beban anggaran, melainkan investasi etis jangka panjang.
Pada akhirnya, cara kita mengelola uang adalah cara kita mengelola makna. Anggaran berbicara tentang siapa kita dan apa yang kita anggap bernilai. Jika demikian, menyusun anggaran seharusnya menjadi latihan kejujuran eksistensial: berani mengakui bahwa setiap angka membawa konsekuensi kemanusiaan.
Maka, sebelum menutup lembar kerja anggaran, mungkin ada baiknya kita bertanya—bukan kepada kalkulator, melainkan kepada nurani: apakah angka-angka ini sudah mencerminkan manusia yang ingin kita perjuangkan?
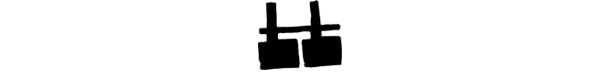
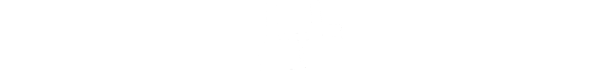
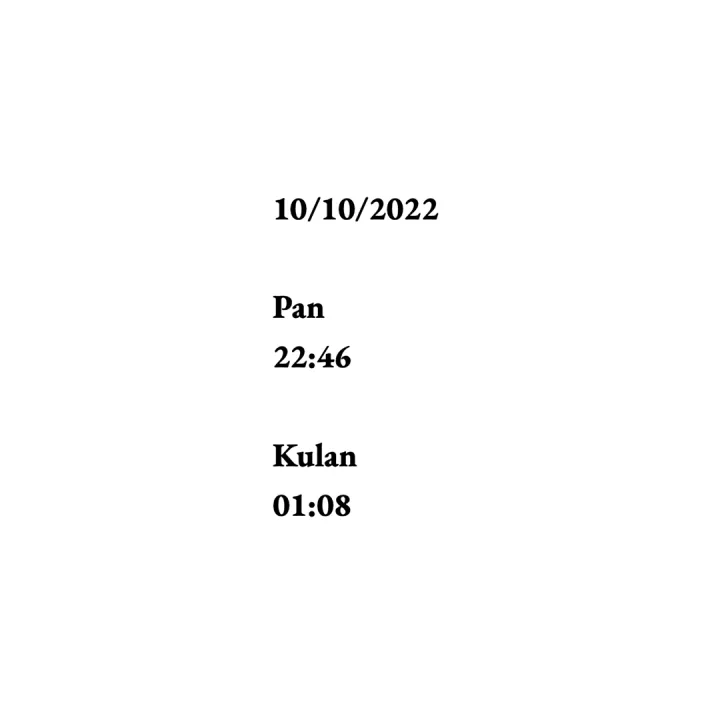
Comments ()